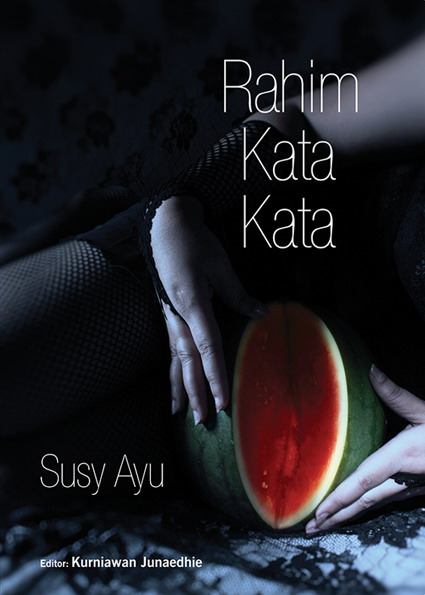PERJAMUAN
ini darahku
sesap baik-baik
ini dagingku
congkel lagi sekepal
di luar
sepi telah resah berkerumun
bagikan saja
sebab tiap sajak cuma gema di Getsemani
tidak, jangan berduka!
aku cuma seorang kekasih
yang bimbang menunggu
di kayu salibmu
(Yogyakarta, 2011-2012)
MENJADI GENANGAN
kamulah Toba
genangan air mata purba
duka yang membeku sebagai dinding kawah
kau kutuk aku dengan cintamu
berjaga sebagai menhir di gerbang-gerbang huta
sampai kau sudahi tujuh puluh tujuh ribu kangenku
dengan selembar kartu pos
yang tak sampai kemanapun
(Bekasi, 2012)
LEBARAN
hatiku sebatang kembang api
kau sulut dan terbakar di awang
sambil kau bertepuk tangan
kumaafkan engkau
untuk kegembiraan yang kekanak-kanakan
(Magelang, 2011)
Minggu, 13 Mei 2012
Kamis, 10 Mei 2012
Seorang Nenek Di Kaki Merapi
setelah puing, setelah asap
setelah tak seorangpun
seorang nenek digendong relawan
ia enggan tak mau pergi
kula mriki mawon
setelah seismologi dan laporan cuaca
setelah early warning system dan disaster management
seorang nenek bersikeras
ia tak beradu pendapat, ia diam
mungkin ada yang tak kita mengerti
pejah gesang kersane Gusti
seorang nenek di kaki Merapi
diusir dari gagasannya
sebab orang tak mau ia seperti Mbah Maridjan
yang kata seorang ustadz
mendzalimi dirinya sendiri
seorang nenek di puing Merapi
berharap menutup wajah dengan kain
berbaring menghadap wuwungan
sembari menyapa maut
dan di gedung kesenian
para penyair berkumpul
membacakan sajak-sajak kepedihan melipur lara
sambil lupa bertanya pada si Nenek
apa sesungguhnya arti selamat
Susy Ayu
Nov 2010
dimuat dalam buku antologi puisi "Merapi Gugat"
setelah tak seorangpun
seorang nenek digendong relawan
ia enggan tak mau pergi
kula mriki mawon
setelah seismologi dan laporan cuaca
setelah early warning system dan disaster management
seorang nenek bersikeras
ia tak beradu pendapat, ia diam
mungkin ada yang tak kita mengerti
pejah gesang kersane Gusti
seorang nenek di kaki Merapi
diusir dari gagasannya
sebab orang tak mau ia seperti Mbah Maridjan
yang kata seorang ustadz
mendzalimi dirinya sendiri
seorang nenek di puing Merapi
berharap menutup wajah dengan kain
berbaring menghadap wuwungan
sembari menyapa maut
dan di gedung kesenian
para penyair berkumpul
membacakan sajak-sajak kepedihan melipur lara
sambil lupa bertanya pada si Nenek
apa sesungguhnya arti selamat
Susy Ayu
Nov 2010
dimuat dalam buku antologi puisi "Merapi Gugat"
Stasiun Tugu Dalam Catatan
STASIUN TUGU 1
di peron lidahmu kelu
sebab telah salah kau tulis
pidato penyambutan untuk sesuatu
yang menjadi keberangkatanmu sendiri
STASIUN TUGU 2
di kursi fiber itu kau termangu
penantianmu sia-sia
sebab entah bagaimana
tak kau sadari adaku
tik tok jam yang setia
menghitung gerbong demi gerbong
juga degup jantungmu sendiri
STASIUN TUGU 3
di jendela
kulihat wajahmu berseliweran
apakah kita pernah berkenalan?
lama kau tak menjawab
sebelum akhirnya kudengar
suara roda menggilas rel
hatiku yang bising dihajar sepi
30 Nov 2010
Susy Ayu
dimuat di Minggu Pagi, Yogya
di peron lidahmu kelu
sebab telah salah kau tulis
pidato penyambutan untuk sesuatu
yang menjadi keberangkatanmu sendiri
STASIUN TUGU 2
di kursi fiber itu kau termangu
penantianmu sia-sia
sebab entah bagaimana
tak kau sadari adaku
tik tok jam yang setia
menghitung gerbong demi gerbong
juga degup jantungmu sendiri
STASIUN TUGU 3
di jendela
kulihat wajahmu berseliweran
apakah kita pernah berkenalan?
lama kau tak menjawab
sebelum akhirnya kudengar
suara roda menggilas rel
hatiku yang bising dihajar sepi
30 Nov 2010
Susy Ayu
dimuat di Minggu Pagi, Yogya
Takluk
seutas g stringku
kau akui adalah mata rantai hilang, yang diburu darwin;
sebab aku adalah manusia yang bermula di Baqqah
dari tanah yang ditiupkan ruh di bentang langit
kau akui
khotbah-khotbahmu telah rubuh di bawah rentang kakiku
kerajaan-kerajaanmu cuma selintas bau samudra
mengingatkan pada keberadaanmu sebagai makhluk pra ampibi,
jauh sebelum mamalia-mamalia merangkak di daratan,
dan kau belum lagi menyusu dari dadaku
kau takluk pada seutas g stringku ***
12 Juni 2010
dimuat dalam buku antologi puisi tunggalku "Rahim Kata-Kata"
kau akui adalah mata rantai hilang, yang diburu darwin;
sebab aku adalah manusia yang bermula di Baqqah
dari tanah yang ditiupkan ruh di bentang langit
kau akui
khotbah-khotbahmu telah rubuh di bawah rentang kakiku
kerajaan-kerajaanmu cuma selintas bau samudra
mengingatkan pada keberadaanmu sebagai makhluk pra ampibi,
jauh sebelum mamalia-mamalia merangkak di daratan,
dan kau belum lagi menyusu dari dadaku
kau takluk pada seutas g stringku ***
12 Juni 2010
dimuat dalam buku antologi puisi tunggalku "Rahim Kata-Kata"
Setangkai Lily Dari Peking
Dulu orang bertanya-tanya, apa yang terjadi jika sebuah benda dibelah terus –menerus, terus dan terus, kecil dan makin kecil? Tak seorangpun bisa melakukannya. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cerdas dan tak henti mempertanyakan kenyataan dunia yang dilihatnya. Kalian tahu apa yang dia katakan? Ia bilang, pekerjaan belah-membelah semacam ini tak bisa dilakukan terus- menerus. Pada akhrinya orng akan tahu bahwa itu pekerjaan mustahil. Itu pelajarannya, seseorang harus berhenti pada waktunya, ia harus menyadari kemampuannya sendiri. Pada saat itulah , orang akan sampai pada bagian yang tak bisa dibagi lagi. Inilah: atom! Dan laki-laki yang cerdas itu bernama Demokritus.
Selain soal Demokritus, aku tercenung oleh ucapan guruku dulu bahwa aku harus menyadari kemampuanku sendiri. Kemampuan bertahan untuk terus tingal di rumah bersama papa, kemampuan untuk mananggung perasaan papa yang terlanjur kehilangan prasangka baik terhadap dunia, hingga mengubah dirinya menjadi lebah pekerja tak bernama di antara kerumunan sejenisnya, mengira bahwa dunia disusun dari berbatang-batang korek api yang bisa dihitung jumlahnya. Aku menyerah untuk menanggungkan papa yang demikian. Papa yang selalu siap melakukan penyederhaan yang picik, mungkin lebih tepat keras kepala, meskipun di atas semua itu papa cuma seorang ayah yang berusaha melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarganya. Kekeraskepalaan papa seringkali membuatnya jauh dari mama dan aku, sungguh ia seorang papa dan suami yang otoriter. Aku menyerah.
Dulu opa adalah pemilik opera Peking. Ia melatih pemain-pemainnya sendiri, mengajari mereka keindahan dan bagaimana hidup dari menciptakan keindahan. Opa dan papa sangat bangga dengan itu, seperti tak ada kehidupan lain di luar itu. Tapi hal-hal terjadi, sebagian terlalu buruk, hidup seperti menumpang di negeri sendiri, tak boleh memilih pakaian kita sendiri, tak boleh merayakan kegembiraan kita sendiri. Aku belum lahir ketika kejadian itu berlangsung. Ada baiknya aku tak merasakan bahwa ada kehangatan dari yang selama ini aku alami.
Kadang aku berpikir, akan lebih baik kalau seseorang tak memiliki kenangan manis. Semua bisa mengubah orang-orang menjadi seperti papa sekarang. Tapi aku tahu, cinta mama membuat papa tak pernah berubah di mata mama. “Papa tetap laki-laki yang hangat, Papa cuma sedang marah. “ Begitu kata mama.
Papa selalu marah menghadapai apapun bahkan untuk segelas air es yang tidak ditemukan di dalam kulkas.
“Bing! Di mana air es?” Papa berteriak.
“Mama bobo,Pa. Mama demam. Air es habis, butuh beberapa jam untuk mendinginkannya lagi. Pa bisa pakai es batu kalau mau.” Aku menjawab dengan kegusaran yang terpendam.
“Mau jadi apa kau ngomong begitu sama orang tua? Aku ngurus pabrik seharian, tahu untuk siapa? Untuk kamu! Kalau aku pulang, apa yang kuinginkan? Air es! Air es tanpa es batu. Ngerti nggak? Kamu mau gantikan Papa ngurus pabrik? Kerjamu cuma sekolah, nonton tv, sibuk foto ini itu. Kalian semua nggak berguna!”
“Papa nggak boleh menghina mama. Papa nggak boleh menghina hobi Lily. Lily cuma bisa motret, Lily senang berada di tempat lain selain di rumah ini, Lily nggak bisa kayak papa ngurus pabrik dan pernah punya opera terkenal.”
Plak! Papa menamparku. Aku berdiri menatapnya tajam. Sementara papa sibuk menciptakan duniaku seperti kisah opera yang bisa dia atur dengan skenario di kepalanya. Apakah papa juga membenciku seperti dia membenci pribumi?
“ Pacaran kamu sekarang sama pribumi?” Suatu hari Papa menegurku dengan keras, di depan rumah ketika Iwan baru mengantarku pulang dari pameran photography. Aku tidak diberinya kesempatan bicara.
“Berapa lama kamu ngabisin duit orang tuamu? 18 tahun? 19 tahun? Dan berapa harga tuh mobil kamu? Puluhan juta, ratusan juta? SMA kamu sudah minta mobil, kalo kuliah kamu minta apa? Ganti mobil yang ada TV nya sekalian? Kamu kuliah, taruh kata tujuh tahun, tigatahun kamu habiskan di diskotik dan pusat pertokoan !” Papa tidak bisa berhenti bicara. Kemarahannya meluap kepada Iwan.
“ Itu untung kalo kamu nggak narkoba. Kalo kamu narkoba, mabuk, ketagihan, orang tuamu akan menghabiskan berapa puluh juta lagi untuk mengirimmu ke rehabilitasi. Dikira saya tidak tahu? Terus berapa ratus juta lagi untuk mobil baru? Biar perasaanmu senang, biar kamu lupa sama narkobamu. Kalau kamu lulus, jadi Insinyur, itu udah untung banget. Kamu akan tetap dibayar untuk bikin diskotik baru, mall baru agar anak-anakmu bisa belanja lebih gila-gilaan lagi. Generasi apa kamu?”
“Tapi om...” Iwan kelabakan. Aku erat menggenggam tangan Mama.
“ Terus hari ini kamu habis bawa anak saya, dengan mobilmu yang warnanya kolokan itu. Kamu mau pamerin ke saya? Ke anak gadis saya?”
“Tapi ,om..saya tidak bermaksud sejauh itu..”
“Oya? Terus kamu mau apa? Kalau saya tidak kasih , kamu hamilin dia nanti. Begitukan caranya? Dikira saya tidak tahu? Terus saya terpaksa kasih anak saya, terus karena kamu nggak bisa kerja, seminggu sekali anak saya akan pulang sambil nangis, minta duit sama saya!”
Saat itu aku adalah gadis 19 tahun yang hidup di negeri seseorang, dengan ayah yang jadi menyebalkan karena tidak boleh bermain barongsai. Tiba-tiba aku merasa menjadi orang Cina, perasaan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Aku tahu, aku memang cina, bermata sipit, seperti beberapa ratus ribu orang lainnya. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Aku belajar Pancasila seperti mereka. Duduk di kelas seperti mereka. Tolol seperti mereka. Aku bertanya-tanya, apakah mereka merasa seperti pribumi?
Dan Iwan memang pribumi di sekolah kami, dan dia bawa mobil. Orang pikir Cina selalu kaya, dan papa mungkin kecewa dengan hidupnya, meski ia pekerja keras. Awalnya aku tidak mau naik mobil Iwan, nanti dikira aku matre. Apalagi aku sipit. Apakah Iwan merasa menjadi cina karena dia pakai mobil dan sekolah di sekolah swasta? Apakah papa merasa jadi pribumi karena dia tingal di negeri ini? Papa tidak bahagia, apapun tidak lagi menyelamatkannya. Aku tidak tahu lagi apa yang dibutuhkan papa, mungkin dia tidak ingin menjadi binatang pencari uang tetapi bagaimana ia bisa tahu hal itu? Dia tidak diijinkan menjadi yang lain, opera opa sudah dibubarkan. Ah, Aku ingin tempat lain, tidak mau duduk di sini, waiting like a fool, menunggu kereta dengan jurusan entah.
Dan kini malam Imlek, seperti dari tahun ke tahun aku merayakan dengan kekhidmatanku sendiri. Tak ada mama, tak ada papa. Kerusuhan Mei telah menghanguskan pabrik papa, merenggut jantungnya untuk kemudian mama menyusul papa dengan cintanya.
Mungkin orang-orang akan megejekku, karena aku Cina, mahasiswi antropologi yang gemar menjadi relawan di tempat yang begitu banyak kematian merenggut. Mungkin di mata orang-orang aku hanya turis yang kebingungan mencari cara untuk pelesir, yang bepergian sejauh ribuan kilo ke sebuah tempat di mana orang –orang saling berbunuhan dengan saudaranya, seperti di Ambon. Juga mengajarkan anak-anak kecil di pengungsian korban Merapi. Kalian bisa saja menuduhku aku bersedih dengan cara yang mewah,mengambil gambar- gambar mereka dan menjadikannya wallpaper di komputer, bersama monumen kesedihanku yang lain.
Benar aku mencari alasan yang paling sederhana untuk melakukan sesuatu, untuk menghidupkan sesuatu, untuk sesuatu yang lebih baik, setidaknya kematian orang tuaku, setidaknya rasa kehilangan, kenangan-kenanganku. Kalian akan mengejekku, tapi mungkin itu satu-satunya hal yang bisa kuraih, untuk bertahan dan berjalan terus. kangen Pa, kangen Ma, kangen rumah. Pa, Ma ayo kita bermain opera Peking dan barongsai, Gong Xi Fa Cai !***
Susy Ayu
dimuat di Minggu Pagi, Yogja, 4 Feb 2011
Selain soal Demokritus, aku tercenung oleh ucapan guruku dulu bahwa aku harus menyadari kemampuanku sendiri. Kemampuan bertahan untuk terus tingal di rumah bersama papa, kemampuan untuk mananggung perasaan papa yang terlanjur kehilangan prasangka baik terhadap dunia, hingga mengubah dirinya menjadi lebah pekerja tak bernama di antara kerumunan sejenisnya, mengira bahwa dunia disusun dari berbatang-batang korek api yang bisa dihitung jumlahnya. Aku menyerah untuk menanggungkan papa yang demikian. Papa yang selalu siap melakukan penyederhaan yang picik, mungkin lebih tepat keras kepala, meskipun di atas semua itu papa cuma seorang ayah yang berusaha melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarganya. Kekeraskepalaan papa seringkali membuatnya jauh dari mama dan aku, sungguh ia seorang papa dan suami yang otoriter. Aku menyerah.
Dulu opa adalah pemilik opera Peking. Ia melatih pemain-pemainnya sendiri, mengajari mereka keindahan dan bagaimana hidup dari menciptakan keindahan. Opa dan papa sangat bangga dengan itu, seperti tak ada kehidupan lain di luar itu. Tapi hal-hal terjadi, sebagian terlalu buruk, hidup seperti menumpang di negeri sendiri, tak boleh memilih pakaian kita sendiri, tak boleh merayakan kegembiraan kita sendiri. Aku belum lahir ketika kejadian itu berlangsung. Ada baiknya aku tak merasakan bahwa ada kehangatan dari yang selama ini aku alami.
Kadang aku berpikir, akan lebih baik kalau seseorang tak memiliki kenangan manis. Semua bisa mengubah orang-orang menjadi seperti papa sekarang. Tapi aku tahu, cinta mama membuat papa tak pernah berubah di mata mama. “Papa tetap laki-laki yang hangat, Papa cuma sedang marah. “ Begitu kata mama.
Papa selalu marah menghadapai apapun bahkan untuk segelas air es yang tidak ditemukan di dalam kulkas.
“Bing! Di mana air es?” Papa berteriak.
“Mama bobo,Pa. Mama demam. Air es habis, butuh beberapa jam untuk mendinginkannya lagi. Pa bisa pakai es batu kalau mau.” Aku menjawab dengan kegusaran yang terpendam.
“Mau jadi apa kau ngomong begitu sama orang tua? Aku ngurus pabrik seharian, tahu untuk siapa? Untuk kamu! Kalau aku pulang, apa yang kuinginkan? Air es! Air es tanpa es batu. Ngerti nggak? Kamu mau gantikan Papa ngurus pabrik? Kerjamu cuma sekolah, nonton tv, sibuk foto ini itu. Kalian semua nggak berguna!”
“Papa nggak boleh menghina mama. Papa nggak boleh menghina hobi Lily. Lily cuma bisa motret, Lily senang berada di tempat lain selain di rumah ini, Lily nggak bisa kayak papa ngurus pabrik dan pernah punya opera terkenal.”
Plak! Papa menamparku. Aku berdiri menatapnya tajam. Sementara papa sibuk menciptakan duniaku seperti kisah opera yang bisa dia atur dengan skenario di kepalanya. Apakah papa juga membenciku seperti dia membenci pribumi?
“ Pacaran kamu sekarang sama pribumi?” Suatu hari Papa menegurku dengan keras, di depan rumah ketika Iwan baru mengantarku pulang dari pameran photography. Aku tidak diberinya kesempatan bicara.
“Berapa lama kamu ngabisin duit orang tuamu? 18 tahun? 19 tahun? Dan berapa harga tuh mobil kamu? Puluhan juta, ratusan juta? SMA kamu sudah minta mobil, kalo kuliah kamu minta apa? Ganti mobil yang ada TV nya sekalian? Kamu kuliah, taruh kata tujuh tahun, tigatahun kamu habiskan di diskotik dan pusat pertokoan !” Papa tidak bisa berhenti bicara. Kemarahannya meluap kepada Iwan.
“ Itu untung kalo kamu nggak narkoba. Kalo kamu narkoba, mabuk, ketagihan, orang tuamu akan menghabiskan berapa puluh juta lagi untuk mengirimmu ke rehabilitasi. Dikira saya tidak tahu? Terus berapa ratus juta lagi untuk mobil baru? Biar perasaanmu senang, biar kamu lupa sama narkobamu. Kalau kamu lulus, jadi Insinyur, itu udah untung banget. Kamu akan tetap dibayar untuk bikin diskotik baru, mall baru agar anak-anakmu bisa belanja lebih gila-gilaan lagi. Generasi apa kamu?”
“Tapi om...” Iwan kelabakan. Aku erat menggenggam tangan Mama.
“ Terus hari ini kamu habis bawa anak saya, dengan mobilmu yang warnanya kolokan itu. Kamu mau pamerin ke saya? Ke anak gadis saya?”
“Tapi ,om..saya tidak bermaksud sejauh itu..”
“Oya? Terus kamu mau apa? Kalau saya tidak kasih , kamu hamilin dia nanti. Begitukan caranya? Dikira saya tidak tahu? Terus saya terpaksa kasih anak saya, terus karena kamu nggak bisa kerja, seminggu sekali anak saya akan pulang sambil nangis, minta duit sama saya!”
Saat itu aku adalah gadis 19 tahun yang hidup di negeri seseorang, dengan ayah yang jadi menyebalkan karena tidak boleh bermain barongsai. Tiba-tiba aku merasa menjadi orang Cina, perasaan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Aku tahu, aku memang cina, bermata sipit, seperti beberapa ratus ribu orang lainnya. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Aku belajar Pancasila seperti mereka. Duduk di kelas seperti mereka. Tolol seperti mereka. Aku bertanya-tanya, apakah mereka merasa seperti pribumi?
Dan Iwan memang pribumi di sekolah kami, dan dia bawa mobil. Orang pikir Cina selalu kaya, dan papa mungkin kecewa dengan hidupnya, meski ia pekerja keras. Awalnya aku tidak mau naik mobil Iwan, nanti dikira aku matre. Apalagi aku sipit. Apakah Iwan merasa menjadi cina karena dia pakai mobil dan sekolah di sekolah swasta? Apakah papa merasa jadi pribumi karena dia tingal di negeri ini? Papa tidak bahagia, apapun tidak lagi menyelamatkannya. Aku tidak tahu lagi apa yang dibutuhkan papa, mungkin dia tidak ingin menjadi binatang pencari uang tetapi bagaimana ia bisa tahu hal itu? Dia tidak diijinkan menjadi yang lain, opera opa sudah dibubarkan. Ah, Aku ingin tempat lain, tidak mau duduk di sini, waiting like a fool, menunggu kereta dengan jurusan entah.
Dan kini malam Imlek, seperti dari tahun ke tahun aku merayakan dengan kekhidmatanku sendiri. Tak ada mama, tak ada papa. Kerusuhan Mei telah menghanguskan pabrik papa, merenggut jantungnya untuk kemudian mama menyusul papa dengan cintanya.
Mungkin orang-orang akan megejekku, karena aku Cina, mahasiswi antropologi yang gemar menjadi relawan di tempat yang begitu banyak kematian merenggut. Mungkin di mata orang-orang aku hanya turis yang kebingungan mencari cara untuk pelesir, yang bepergian sejauh ribuan kilo ke sebuah tempat di mana orang –orang saling berbunuhan dengan saudaranya, seperti di Ambon. Juga mengajarkan anak-anak kecil di pengungsian korban Merapi. Kalian bisa saja menuduhku aku bersedih dengan cara yang mewah,mengambil gambar- gambar mereka dan menjadikannya wallpaper di komputer, bersama monumen kesedihanku yang lain.
Benar aku mencari alasan yang paling sederhana untuk melakukan sesuatu, untuk menghidupkan sesuatu, untuk sesuatu yang lebih baik, setidaknya kematian orang tuaku, setidaknya rasa kehilangan, kenangan-kenanganku. Kalian akan mengejekku, tapi mungkin itu satu-satunya hal yang bisa kuraih, untuk bertahan dan berjalan terus. kangen Pa, kangen Ma, kangen rumah. Pa, Ma ayo kita bermain opera Peking dan barongsai, Gong Xi Fa Cai !***
Susy Ayu
dimuat di Minggu Pagi, Yogja, 4 Feb 2011
Puisi-Puisi SA di Minggu Pagi, Yogya
Puisi-puisi Susy Ayu di koran Minggu Pagi, Yogyakarta, Jumat Kliwon 14 Oktober 2011
SAJAK SEEKOR BADAK
(untuk 50 ekor badak jawa yang hampir punah di ujung kulon)
saat kau resah dan sendiri
bersembunyilah di sini
pada kubangan pada sesemakan
pada tiga goresan culaku di batang-batang pohon
tunggu ia datang
mengukur jejakmu
menebak adamu
menghitung hidupmu
di dalam sini
sembunyimu abadi
dengan limapuluh ekor kesunyian
di Dandaka-Dandaka rahasia
sebelum Baratayudha
8 Maret 2011
PADA SUATU MASA DI KELENTENG MA ZU
561 tahun keabadian
cintaku kokoh meresap
dalam tiang jati kelenteng tertua
tegak menghadap langit tanah Jawa
ketika angin berwajah gelisah
telah kutitipkan nama kita
pada arak-arakan kio keemasan
anggun melintasi gerbang Ma Zu
Lasem, April 2011
TERSESAT
orang sudah berbunuhan sejak jaman dulu
ini semua bukan hal baru
dan masih saja berulang
mereka mencari jalan pulang masing-masing
dan tak habis-habis mempertengkarkan cara yang mereka tempuh
kelak anak-anak kita juga mencari jalan pulang
tapi dari mana semua itu hendak dimulai ?
tidakkah kita cemas mereka akan tersesat
jika hanya kebencian yang diwariskan?
ada banyak kuburan di tempat ini
ada lebih banyak lagi di benak orang-orang
mereka menziarahinya tiap kali
setiap kali disadari ada yang sudah hilang
mereka akan menengok ke sekeliling
tak tahu lagi apakah kesedihan atau kematian
yang membuat mereka saling melukai
kelak anak-anak kita adalah si penyampai pesan
yang semua pesan adalah berita baik
bukankah setiap nabi juga membawa pesan baik?
namun pengikutnya memperlombakan kebaikannya
hingga saling membunuh untuk memenangkannya
mereka lupa bahwa Tuhan yang menciptakan segala
nabi-nabi itu, kebaikan kebaikan itu
mereka lalai bahwa jalan pulang hanya kepada Tuhan
Tuhan satu-satunya tempat semua pesan itu berasal
Oktober 2011
OPERA SEMALAM 2
kita duduk berdua di depan televisi
“Kita sudah kebingungan. Kita panggil para ahli dari luar negeri dan
bersikap seakan formulasinya adalah obat paling mujarab untuk segala
penyakit. Kita berkerumun seperti nonton tukang obat di pasar. Anda
ngerti tho maksud saya?”
kita duduk berdua di depan televisi, mengganti saluran lain
“negeri ini penuh krisis, tidak semata-mata krisis politik, melainkan
krisis multidimensi. Rakyat sudah tidak percaya lagi lagi pada
kepemimpinan yang ada “
kita duduk berdua di depan televisi, menekan saluran lain
“Indonesia mmng sedang membususk. Mental kita belum mampu
berdemokrasi. Amerika melewati tahap anarkis sebelum akhirnya
membentuk masyarakat sipil mereka. Perbudakan, perang saudara,
wildwest.”
kita berdua masih duduk di depan televisi, mematikannya
bapakku terbunuh di atas sajadah
ayahmu meninggal kena ledakan bom gereja
haruskah ada seseorang yang mati lebih dulu untuk memberikan alasan
atas cita-cita kemanusiaan?
Tuhan, Kau ada di saluran berapa?
Oktober 2011
SAJAK SEEKOR BADAK
(untuk 50 ekor badak jawa yang hampir punah di ujung kulon)
saat kau resah dan sendiri
bersembunyilah di sini
pada kubangan pada sesemakan
pada tiga goresan culaku di batang-batang pohon
tunggu ia datang
mengukur jejakmu
menebak adamu
menghitung hidupmu
di dalam sini
sembunyimu abadi
dengan limapuluh ekor kesunyian
di Dandaka-Dandaka rahasia
sebelum Baratayudha
8 Maret 2011
PADA SUATU MASA DI KELENTENG MA ZU
561 tahun keabadian
cintaku kokoh meresap
dalam tiang jati kelenteng tertua
tegak menghadap langit tanah Jawa
ketika angin berwajah gelisah
telah kutitipkan nama kita
pada arak-arakan kio keemasan
anggun melintasi gerbang Ma Zu
Lasem, April 2011
TERSESAT
orang sudah berbunuhan sejak jaman dulu
ini semua bukan hal baru
dan masih saja berulang
mereka mencari jalan pulang masing-masing
dan tak habis-habis mempertengkarkan cara yang mereka tempuh
kelak anak-anak kita juga mencari jalan pulang
tapi dari mana semua itu hendak dimulai ?
tidakkah kita cemas mereka akan tersesat
jika hanya kebencian yang diwariskan?
ada banyak kuburan di tempat ini
ada lebih banyak lagi di benak orang-orang
mereka menziarahinya tiap kali
setiap kali disadari ada yang sudah hilang
mereka akan menengok ke sekeliling
tak tahu lagi apakah kesedihan atau kematian
yang membuat mereka saling melukai
kelak anak-anak kita adalah si penyampai pesan
yang semua pesan adalah berita baik
bukankah setiap nabi juga membawa pesan baik?
namun pengikutnya memperlombakan kebaikannya
hingga saling membunuh untuk memenangkannya
mereka lupa bahwa Tuhan yang menciptakan segala
nabi-nabi itu, kebaikan kebaikan itu
mereka lalai bahwa jalan pulang hanya kepada Tuhan
Tuhan satu-satunya tempat semua pesan itu berasal
Oktober 2011
OPERA SEMALAM 2
kita duduk berdua di depan televisi
“Kita sudah kebingungan. Kita panggil para ahli dari luar negeri dan
bersikap seakan formulasinya adalah obat paling mujarab untuk segala
penyakit. Kita berkerumun seperti nonton tukang obat di pasar. Anda
ngerti tho maksud saya?”
kita duduk berdua di depan televisi, mengganti saluran lain
“negeri ini penuh krisis, tidak semata-mata krisis politik, melainkan
krisis multidimensi. Rakyat sudah tidak percaya lagi lagi pada
kepemimpinan yang ada “
kita duduk berdua di depan televisi, menekan saluran lain
“Indonesia mmng sedang membususk. Mental kita belum mampu
berdemokrasi. Amerika melewati tahap anarkis sebelum akhirnya
membentuk masyarakat sipil mereka. Perbudakan, perang saudara,
wildwest.”
kita berdua masih duduk di depan televisi, mematikannya
bapakku terbunuh di atas sajadah
ayahmu meninggal kena ledakan bom gereja
haruskah ada seseorang yang mati lebih dulu untuk memberikan alasan
atas cita-cita kemanusiaan?
Tuhan, Kau ada di saluran berapa?
Oktober 2011
Aristoteles Dan Fiksi Mini
Menurut aristoteles, yg menelurkan salah satu teori cerita paling tua yaitu sebuah cerita memiliki awalan, tengah dan akhir. (Struktur tiga babak.) Jika kita mengikuti teori itu, meskipun itu bukan teori satu satunya, maka semestinya sebuah fiksi memiliki unsur-unsur tsb. Awalan sebagai perkenalan (bisa berupa kalimat tersirat) , tengah itu puncak konflik, akhir adalah solusi atau resolusi.
Awalan, puncak maupun resolusi/solusi mengacu pd struktur bukan pada kronologi, artinya; urutannya bisa dibolak-balik atau bahkan berhimpit satu sama lain. Justru di sinilah yg menjadikan kekuatan sebuah fiksimini. Tantangannya adalah bagaimana memenuhi unsur-unsur itu di dalm 140 karakter yg sebaiknya mengandung : aspek yg baik dr sebuah cerita yaitu suspense atau surprise.
Fiksimini merupakan sebentuk wahana di mana eksperimentasi seprti itu dilakukan. Kemudian akan menjadi lengkap ketika pembaca bisa menangkap premis yang melandasi plot dlm cerita itu. Premis ini sendiri biasa merupakan gagasan tersembunyi yang sebaiknya tdk pembaca temukan pd kesempatan pertama perjumpaannya dgn teks sehingga sebuah fiksimini bisa terhindar dr deretan slogan maupun definisi-definisi yg terlalu verbal.
Pertanyaan dari mas S che Hidayat:
S Che Hidayat ::. Fiksimini - Mucikari -
( ini hanya copas)
Semalam lagi terlewat, dalam dada perih teriris, uang yang digenggamnya tak cukup meski hanya untuk membayar terapi HIV-nya.
adakah dari ketiga unsur di atas -yang di sebutkan kak SusyAyu Dua, di fiksimini itu.
sengaja saya ambil contoh dari tulisan saya sendiri...
terima kasih.
Jawaban :
SusyAyu Dua
Mas S Che Hidayat,ya. ada. Frase "semalam lagi terlewat" merupakan introduksi pd pembaca bahwa plot yang dijabarkan sesudahnya merupakan proses yang sudah berkelanjutan, berhimpit-himpit dengan surprise "uang yang digenggamnya tak cukup" yang merupakan puncak konflik dan sekaligus resolusi dari plot.
Ada baiknya juga untuk menggarisbawahi bahwa seringkali dalam fiksi mini, bagian-bagian yang merupakan introduksi, puncak dan resolusi hanya bisa dikenali sebagai 'lengkap' ketika ketiganya telah ditandai oleh pembaca. Himpitan-himpitan semacam ini yang merupakan salah satu kekhasan fiksi mini, dan juga sekaligus kekuatannya.
Keterbatasan ruang (yang inipun hanya berlaku dalam ‘rubrik’ ini, yakni 140 karakter) yang sudah didefiniskan sebelumnya memberi keharusan untuk mengasah kesanggupan menuangkan gagasan dalam 'ketidaklengkapan-ketidaklengkapan' yang musti berefek 'lengkap' dalam imajinasi pembaca.
Masalahnya adalah apakah kisah yang ditulis cukup seduktif untuk membuat pembaca melengkapinya sendiri dalam gagasan yang terbit dalam benak mereka setelah membacanya?
Demikianlah salah satu kemenarikan dari fiksi mini. Seduksi, suspense, surprise.. mungkin demikian yang bisa diangankan dari sebuah fiksi mini. Tentu saja ini juga bukan segalanya :)
Buat teman yg ingin mengetahui teori dasar ttg struktur tiga babak ini, bisa dibaca di buku Poetics-nya Aristoteles
Dalam bukunya, Poetics, Aristoteles, banyak menelaah tentang tragedi, sebuah bentuk dramatik yang banyak ditemukan dalam sebagian besar literatur klasik Yunani. Menurutnya, sebuah tragedi memiliki enam bagian yang mendasar, yaitu Plot, Karakter, Diksi, Ide (Thought), Spektakel (spectacle) dan Lagu (Song). Dalam hal plot, demikian yang ia katakan:
The plot, then, is the first principle, and, as it were, the soul of a tragedy:…
Dan lanjutnya:
Chapter VII
.. Tragedy is an imitation of an action that is complete, and whole, and of a certain magnitude; .. A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. A beginning is that which does not itself follow anything by causal necessity, but after which something naturally is or comes to be. An end, on the contrary, is that which itself naturally follows some other thing, either by necessity, or as a rule, but has nothing following it. A middle is that which follows something as some other things follows it. A well constructed plot, therefore, must neither begin nor end at haphazard, but conform to these principles.
Bila disimak, mungkin bisa ketemukan banyak sekali karya-karya sekarang ini yang tidak sepenuhnya memenuhi yang dijabarkan dalam Poetics, tapi demikianlah jamaknya sebuah teori, yang akan terus direvisi dari waku ke waktu. Akan tetapi, dalam kesempatan pertama, penjabaran teori-teori ‘babon’ semacam ini menarik untuk disimak, karena demikianlah pondasi pengertian kita akan kenyataan (karya sastra) bisa kita tetapkan. Sebuah pondasi semata-mata tentu saja tidak memadai, tapi kita tetap memerlukannya sebagai dasar bukan?
Dalam hal fiksi mini kita, tentu saja kita bisa melampaui teori itu, atau teori manapun, dan memang seharusnyalah demikian, sebuah karya kreatif semestinya terbebas dari aturan. Tapi ketika kita ingin melampaui aturan, bukankah aturan itu sendiri harus kita kenali? Dan tentu saja, sekali lagi, ini juga bukan satu-satunya aturan.
Sekelumit tulisan tentang gagasan aristoteles mengenai struktur tiga babak ini sekali lagi bukan agar fiksimini yang kita tulis hanya memenuhi hal tersebut, tapi justru agar eksperimen-eksperimennya dapat melampaui kebakuan-kebakuan yang ada. Demikian takdir yang mestinya ditempuh oleh sastra.
Terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. ***
(tulisan ini berawal dr status saya untuk menyemangati dan memberi masukan yang lebih praktis kepada teman-teman peserta # fiksi 140, namun kemudian berkembang menjadi sebuah note seperti ini).
Susy Ayu
Pelaku Sastra
27 Oktober 2011
Awalan, puncak maupun resolusi/solusi mengacu pd struktur bukan pada kronologi, artinya; urutannya bisa dibolak-balik atau bahkan berhimpit satu sama lain. Justru di sinilah yg menjadikan kekuatan sebuah fiksimini. Tantangannya adalah bagaimana memenuhi unsur-unsur itu di dalm 140 karakter yg sebaiknya mengandung : aspek yg baik dr sebuah cerita yaitu suspense atau surprise.
Fiksimini merupakan sebentuk wahana di mana eksperimentasi seprti itu dilakukan. Kemudian akan menjadi lengkap ketika pembaca bisa menangkap premis yang melandasi plot dlm cerita itu. Premis ini sendiri biasa merupakan gagasan tersembunyi yang sebaiknya tdk pembaca temukan pd kesempatan pertama perjumpaannya dgn teks sehingga sebuah fiksimini bisa terhindar dr deretan slogan maupun definisi-definisi yg terlalu verbal.
Pertanyaan dari mas S che Hidayat:
S Che Hidayat ::. Fiksimini - Mucikari -
( ini hanya copas)
Semalam lagi terlewat, dalam dada perih teriris, uang yang digenggamnya tak cukup meski hanya untuk membayar terapi HIV-nya.
adakah dari ketiga unsur di atas -yang di sebutkan kak SusyAyu Dua, di fiksimini itu.
sengaja saya ambil contoh dari tulisan saya sendiri...
terima kasih.
Jawaban :
SusyAyu Dua
Mas S Che Hidayat,ya. ada. Frase "semalam lagi terlewat" merupakan introduksi pd pembaca bahwa plot yang dijabarkan sesudahnya merupakan proses yang sudah berkelanjutan, berhimpit-himpit dengan surprise "uang yang digenggamnya tak cukup" yang merupakan puncak konflik dan sekaligus resolusi dari plot.
Ada baiknya juga untuk menggarisbawahi bahwa seringkali dalam fiksi mini, bagian-bagian yang merupakan introduksi, puncak dan resolusi hanya bisa dikenali sebagai 'lengkap' ketika ketiganya telah ditandai oleh pembaca. Himpitan-himpitan semacam ini yang merupakan salah satu kekhasan fiksi mini, dan juga sekaligus kekuatannya.
Keterbatasan ruang (yang inipun hanya berlaku dalam ‘rubrik’ ini, yakni 140 karakter) yang sudah didefiniskan sebelumnya memberi keharusan untuk mengasah kesanggupan menuangkan gagasan dalam 'ketidaklengkapan-ketidaklengkapan' yang musti berefek 'lengkap' dalam imajinasi pembaca.
Masalahnya adalah apakah kisah yang ditulis cukup seduktif untuk membuat pembaca melengkapinya sendiri dalam gagasan yang terbit dalam benak mereka setelah membacanya?
Demikianlah salah satu kemenarikan dari fiksi mini. Seduksi, suspense, surprise.. mungkin demikian yang bisa diangankan dari sebuah fiksi mini. Tentu saja ini juga bukan segalanya :)
Buat teman yg ingin mengetahui teori dasar ttg struktur tiga babak ini, bisa dibaca di buku Poetics-nya Aristoteles
Dalam bukunya, Poetics, Aristoteles, banyak menelaah tentang tragedi, sebuah bentuk dramatik yang banyak ditemukan dalam sebagian besar literatur klasik Yunani. Menurutnya, sebuah tragedi memiliki enam bagian yang mendasar, yaitu Plot, Karakter, Diksi, Ide (Thought), Spektakel (spectacle) dan Lagu (Song). Dalam hal plot, demikian yang ia katakan:
The plot, then, is the first principle, and, as it were, the soul of a tragedy:…
Dan lanjutnya:
Chapter VII
.. Tragedy is an imitation of an action that is complete, and whole, and of a certain magnitude; .. A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. A beginning is that which does not itself follow anything by causal necessity, but after which something naturally is or comes to be. An end, on the contrary, is that which itself naturally follows some other thing, either by necessity, or as a rule, but has nothing following it. A middle is that which follows something as some other things follows it. A well constructed plot, therefore, must neither begin nor end at haphazard, but conform to these principles.
Bila disimak, mungkin bisa ketemukan banyak sekali karya-karya sekarang ini yang tidak sepenuhnya memenuhi yang dijabarkan dalam Poetics, tapi demikianlah jamaknya sebuah teori, yang akan terus direvisi dari waku ke waktu. Akan tetapi, dalam kesempatan pertama, penjabaran teori-teori ‘babon’ semacam ini menarik untuk disimak, karena demikianlah pondasi pengertian kita akan kenyataan (karya sastra) bisa kita tetapkan. Sebuah pondasi semata-mata tentu saja tidak memadai, tapi kita tetap memerlukannya sebagai dasar bukan?
Dalam hal fiksi mini kita, tentu saja kita bisa melampaui teori itu, atau teori manapun, dan memang seharusnyalah demikian, sebuah karya kreatif semestinya terbebas dari aturan. Tapi ketika kita ingin melampaui aturan, bukankah aturan itu sendiri harus kita kenali? Dan tentu saja, sekali lagi, ini juga bukan satu-satunya aturan.
Sekelumit tulisan tentang gagasan aristoteles mengenai struktur tiga babak ini sekali lagi bukan agar fiksimini yang kita tulis hanya memenuhi hal tersebut, tapi justru agar eksperimen-eksperimennya dapat melampaui kebakuan-kebakuan yang ada. Demikian takdir yang mestinya ditempuh oleh sastra.
Terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. ***
(tulisan ini berawal dr status saya untuk menyemangati dan memberi masukan yang lebih praktis kepada teman-teman peserta # fiksi 140, namun kemudian berkembang menjadi sebuah note seperti ini).
Susy Ayu
Pelaku Sastra
27 Oktober 2011
Kunamai Kau Kenangan
Aku melihatmu di tengah kerumunan, dengan pucat yang memasi di seluruh mu. Tanah pijakanku serasa bergetar disaat kaki mungil bersepatu kets mu menjejak dari atas kereta malam terakhir. Udara malam kini menamparku berkali-kali dari keterpesonaan.
" Menepilah…!"
Sebelah tanganmu menutup wajah, ketika darah terpercik dari kerumunan. Sebelah lagi kau biarkan kuraih untuk menepi.
"Tidak seharusnya dia diperlakukan begitu…dia hanya pencopet kecil…" suaramu merintih.
Sungguh aku yang terkapar, kau curi semua rasa di dalam hatiku dengan bibir gemetarmu, wajah pucatmu terus menerus menggantung di pelupuk mata. Kau bangkitkan aku berkali-kali.
Kau bilang kau pernah membenci kota ini, bahkan mungkin masih tersisa itu di dalam hatimu. Tapi sesuatu hal membawamu kemari, sendiri, dan pertemuan tak terduga ini mencipta banyak hal diluar kuasaku.
Kau cuma bergumam, dengan kalimat yang sulit kumengerti maknanya, bahwa alur hidupmu berubah di kota ini. Kota yang berpakaian sangat santun ini sanggup mencabik habis seluruh lorong nafasmu. Kau membenci tempatku menatap bintang sepanjang malam. Tapi disebaliknya, kau duduk bersebelahan denganku, cuma ini caramu mencintai rasa sakitmu, kau bilang begitu.
Tapi aku tidak cukup punya waktu untuk berusaha memahamimu, pun untuk memahami ledakan-ledakan dari suram di dalam sini. Aku berharap sedikit saja cahaya dari mendung di atas langit rumahku, tapi kau memberi banyak, lebih dari bulan yang sengaja purnama. Di usia hampir tiga puluhku ini, percayakah kau jika ku katakan bahwa cinta pertama kali datang untukku?
Aku selalu berharap kau percaya geletar pertama yang bangkit sebagai pengetahuan, ini adalah sesuatu yang kita sebuat cinta. Dan kau yang mebawanya ke rumahku, aku melihat geletar dimatamu yang tidak sependapat denganku.
"Apa artinya,." katamu. Tidak memberikan makna apa-apa dalam hidup, apakah dia datang yang pertama atau kesekian. Bagimu itu hanya dongeng-dongeng kepedihan yang terus menerus diturun temurunkan. Kenangan yang memaksakan diri untuk mencipta rasa bahagia bagi orang-orang yang merasa kehilangan.
Ah, tidak, aku tidak ingin membuat deretan kenangan di bumi ini tentang sebuah kisah cinta pertama. Memalukan, kita berdebat di rumput rumahku hanya karena sebuah cinta yang datang pertama kali. Tapi jika kau ijinkan aku bersumpah, aku ingin membelah langit dengan semburat dari matamu, sinar itu tentu akan sanggup, seperti ia telah membelah dadaku dan meninggalkan bongkahan besar untuk selalu kusimpan.
***
Kau mulai menyibakkan selubung kelabumu dengan sebuah kisah seperti hujan yang sangat sedikit, tentang kebencianmu yang membuatmu selalu merasa terdampar di kota ini sekaligus membuatmu ingin kembali dan kembali, meski tanpa kekuatan.
Kala itu, berbaring dalam telanjang di tengah jerami kering, Jogja, memanggilmu "perawan". Tapi engkau bukan Maria, dan juga bukan bayimu (yang tak sempat lahir) adalah Jesus.
"Tapi telah kuberikan cintaku seutuhnya!" sergahmu.
Tetap saja, sejarah mengancingkan celananya dan berpaling. Maka dengan pedih di selangkanganmu kau teruskan hidupmu. Kota itu pun bangkit dari tidur ayamnya dan mencegahmu berpamitan.
Kau lalu memang menyelinap darinya sambil terus menyusun kiat yang lebih nyaman untuk berselingkuh dengan dirimu sendiri, sebab semua kota cuma hamparan lendir bagimu. Kau terus berjalan karenanya, sampai kemudian kau temui laki-laki lain itu, yang telapak tangannya berlubang. Dan selain alasan penyaliban atas dirinya sendiri, ditempuhnya sekarat untuk ia sampaikan pesan ini : Bahwa Engkau tak berdosa Bahwa kota itu, yang adalah kota ini, tetap memanggilmu "perawan!"Kau menyusut air matamu perlahan.
Tapi ternyata musim berdusta tak bertahan lama, kau terkoyak lagi, oleh sebuah penuntutan yang tak bisa mengadili dengan adil. Kau tetap saja seorang perempuan yang tidak sebening embun ketika matahari mulai terbangun walau hanya kota ini yang tetap memanggilmu perawan.
Kau ciptakan sungai dan senja, di sebalik kenanganmu yang sarat oleh siksa, juga di telapak tanganmu. Warna jingga keunguan kau semburatkan di ujung jari. Jika makna alirku serupa batu hitam di dasar berlumut, hanya senjamu yang dapat menghapus warna laut. Abadikan ia dalam remasan tanganmu. Dan kapal-kapal akan terselip di rambutku. Badai akan tercipta dari helai-helai gairah yang berguguran. Mengalir, mengalirlah kata-katamu di sungai mu. Senja merah yang sangat kusuka. Tanganmu kekal meremas punggunggku.
Lalu kau menangis…..
Dengarlah perempuan yang kutemui dalam separuh perjalananku, aku adalah batu hitam yang diam itu. Sebermula adalah wujud untuk kemudian menjadi ada. Dari ada lalu terbit kesedihan, dan pada kesedihan hinggap kehidupan. Bersamanya, hinggap pula engkau. Maka cuaca telah mempertemukan kita. Dan senja yang kau ciptakan memperlembut kemarau, menaburkan embun dan menumbuhkanmu. Akarmu lembut menggemburkanku. Lalu dalam musim, kau mengikisku, butir demi butir, tanpa aduh, tanpa keluh.
Kau telah menghidupkan aku dalam urai. Untuk kemudian larut sebagai gembur, tempat di atasnya kau beranak pinak, menghampar hijau tengadah menentang matahari. Bersediakah kau menikah denganku nanti?
Kau cuma menangis….(lagi)
Sementara putingmu bergeser di punggungku, aku bercerita bahwa sebatang selokan ini Rajaku yang bikin. Ketika Opak dan Progo bertemu, maka Mataram akan menjadi rahim bagi kelanggengan. Ketika kemudian sungai darahmu dan sungai darahku menyatu tak lama kemudian, tidakkah gagasan tentang keabadian Mataram itu begitu syahwati? Tak kau jawab tanyaku.
Matamu maut yang padam menatapku, dan cengkeraman kukumu di punggunggku…Ah..keabadian adalah sedetik sebelum kau tertelungkup, sungai hidupmu mengalir, sungai hidupku mengalir, dalam gelimang cahaya bulan di permukaan selokan Mataram.
Kau telah menemukanku, yang tersesat dalam kabut. Ketika kupanggil namaku, tapi cuma gaungnya sendiri. Lalu hujan turun, lagi, bertahun kemudian. Masih saja tak ada siapapun. Cuma sepotong sajak yang menegaskan aduhku. Hujan turun di rumput. Ada juga hujan untukku, dan Nuh. Tapi tak akan aku bersamanya, sebab bahkan belibis pun berpasangan di danau itu. Siapa gerangan aku, laki-laki, di padang ini, di Timur Sorga, tanpa Hawa?
Ingin kusebut engkau ibuku, yang telah memberiku koin, untuk membuatku menempuh level berikutnya. Kau telah membuatku terus menerus merasa berharga, sebab koin-koin membuat pertempuran terus ada, dan akulah pemenangnya. Meski bila tidak, kau selalu memberiku nafas, seperti koin yang terus selalu ada untuk pertarungan berikutnya.
Ingin ku sebut kau adalah ibuku, yang dari putingmu terus menggelinding koin-koin berikutnya, gairah hidupku, rasa adaku. Kau yang telah menemukanku! Tidak sekedar sebuah cinta baru tumbuh di hati yang berkarat. Kau menarikku dari tempatku tinggal, membuka mata hati untuk berusaha melihat bahwa jalan ini tidak seburuk yang kukira. Patahan-patahan semangat kau susun, seperti menjahit perca demi perca. Kau mencipta aku, wahai perempuan. Lebih dari sekedar jasadmu yang terbangun dari tulang rusukku. Ah, karena itukah yang membuatku lemah…sementara kau tidak perempuan, tak ada yang mengurangi rusukmu.
Kupikir kita telah menggenggam harapan, ketika kita menautkan apa yang disebut cinta. Terlambatkah itu menyerbuku? Lalu kaupun berkemas, sebelum mengakhirinya dengan sebuah selamat tinggal yang ganjil. Tapi kereta selalu tak mau menunggu, meskipun ia selalu bisa saja berangkat telat, seperti semua kekasih yang mengkhianatimu.Hingga malam itu, dalam lengking yang terdengar seperti peluit terakhir, malam menelanmu bulat-bulat, dengan suara gemuruh yang masih saja bergema sebagai separo mimpi separo jaga hingga dua puluh tujuh purnama kemudian.
Aku mengenangmu sebagai suara gemuruh yang hilang di ujung stasiun, mengingatnya lagi dan lagi, bertalu-talu dalam nadiku. Hingga kemudian, ia menyatu sebagai degup jantungku. Demikianlah engkau tinggal dalam diriku, jauh sesudah semua pengkhianatan yang paling pedih dilupakan orang, dan bahkan tidak bisa kueja lagi sejarahmu sebagai kata-kata. Engkau tinggal di sekelilingku sebagai cuaca yang memerangkapku dari musim ke musim.
Tapi pun aku tahu, kau mengambang juga di langit kotamu. Memerangkap sekian laki-laki lain dalam cuaca. Aku tahu. Aku tahu. Pengkhianatan telah menjadikanmu begitu lihai mengemas kegetiran. Dan kereta malam terakhir itu telah benar-benar merampasmu dari heningku yang sudah mulai bingar. Kau selimuti engganmu dengan senyum , dari sebalik jendelamu kutanggap keberatan itu. Tangan yang dipaksa untuk melambai tanpa gerak, melekat. Aku berlari, coba menyusulmu, mengiringi lajunya. Kau terampas, aku terkapar, aku harap ini hanya sejenak. Sekedipan mata. Kelak aku ingin kita bertemu lagi.
Kau tahu, di seberang pengkhianatan, tidak ada lagi yang cukup pedih untuk menjadi sebuah roman yang mengharukan, pun juga tidak celotehan tolol separo-mimpi-separo jaga ini. Kelak, aku akan cuma jadi laki-laki kesekian dalam hidupmu. Laki-laki kesekian yang tidak penting lagi untuk mencintaimu atau mengkhianatimu. Tapi aku mengingatmu, sebagai gemuruh yang lenyap di ujung stasiun.
Satu-satunya ingatan yang diijinkan kumiliki, sebelum membeku sebagai sebongkah batu, yang cuma bisa merasakan kesunyian, tapi tak bisa menamainya. Ya, aku tak bisa menamaimu. Aku merasakanmu, mengingatmu, tapi tak bisa kunamai kenanganku.
Kelak, perempuan, bila tiba saatnya, aku akan menemuimu, setelah kusesap lagi Buah Pengetahuan sekali lagi, terkutuk untuk kedua kalinya, terlempar dari diam ini, mencarimu di muka bumi, terperangkap di bawah kolong langit. Sebab, perempuan, sebab it is you that invented me.
******
Ah….Dimanakah kau, Mbak?
Betapa tololnya aku, setelah habis hembusan rokokku berbatang-batang baru kusadari kau begitu jauh dariku. Berapa jarak kita, Mbak? Ratusan kilometer ini menjamahku dari tenang di sisimu. Kau ada di jarak itu, dalam sebuah rumah, dimana seorang laki-laki menjaga pintunya, dan di kakinya kau bersimpuh, membasuhnya. Mungkin bukan, kau adalah putri itu, yang selendang putihnya melambai oleh angin di pucuk menara, dengan naga melingkar di jenjangnya, dengan mantra mengambang di gerbangnya. Di sana, aku tahu, seorang nenek sihir menjelma laba-laba tua yang sarangnya memenjaramu.
Tracy Chapman di layar, menggantung di depan stage. Di atasku, langit menyingkap, bintang-bintang, ah. Sebatang lilin bertahan dari gerimis di sebuah cekungan, mencegahmu untuk tidak terperosok di sana, lalu bangku-bangku , dan kursi, music itu, gadis –gadis bak boneka keramik itu, sejumlah pasangan yang bergeremang dalam gelap. Kupikir kopi ini terlalu pahit, mungkin aku membutuhkan tambahan gula. Ketika waitress itu mendekat, ia mendekatkan telinganya ke mulutku, "Apakah saya bisa minta tambahan gula lagi?"
Kupikir aku adalah seorang pengembara, menyalakan unggunan api di seberang jendelamu. Kulihat kau berdandan, nun di atas sana, dan selendang itu masih saja melambai oleh angin. Ketika kusesap kopiku, dari balik lidah api itu, kesedihan menyerbu dengan cara yang sangat menyakitkan; untuk siapakah gerangan, Her majesti, engkau berdandan? Sungguh angin begitu jahat di luar sini. Dan sunyi ini merubung tak tertahankan. Pun langit tetap saja melengkung tanpa jawaban. Kenapa kita tidak bercakap saja, berdiang dengan kata-kata ; mungkin tidak, mungkin cuma bertatapan, atau bercinta begitu saja, seperti sepasang serangga.
Lalu, sejumlah permaafan, atas jarak itu, laki-laki itu, nenek sihir itu, naga yang melingkar itu, mantra itu, menara itu, adaku dan adaku, yang tak bersisian. Ketika aku mendongak, kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali.
Seseorang memanggil namaku, "Maukah kau memberi pengantar untuk pertunjukan kita malam ini?"
Menempuh meja-meja itu, gerimis membungkusku, dan di bawah lampu aku tersenyum pada penonton yang tak kukenal dan berkerumun dalam remang. Ia mati muda, kataku, seperti Chairil Anwar, Soe Hok Gie, atau Nike Ardilla. Kerumunan itu tidak menjawab, aku tahu, aku bicara untuk diriku sendiri, sebab aku adalah laki-laki di bawah sorot lampu.
Aku berharap kau ada di sana, meskipun tak kulihat kau dalam gelap. Aku berharap kau menungguku, setelah aku turun dari panggung, menempuh meja-meja, pasangan yang bergenggaman, dentum musik dan sorot lampu. Aku berharap kau menungguku, untuk saling berbisik lagi, dan menjadikanku laki-laki yang tidak bicara pada dirinya sendiri.
Dalam benakku, kutemukan kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali. Hallo, can I call You, Mbak? Tengah malam ini, kutulis sebuah surat panjang untukmu.
Aku belum bisa terlelap. Kamu sedang apa?
Sender: mbak
+ 6281284XXXXX
Boleh aku menelponmu, mbak? Sebentar saja.
Send.Klik
Delivered
Tidak perlu! Dia memang tidak pulang lagi malam ini.
Aku hanya ingin tahu kamu baik-baik saja.
Irit-irit pulsamu. Selamat tidur ya?
Sender: mbak
+ 6281284XXXXX
***
Dalam tidurmu kau bergumam. Dan ketika kusadari bahwa hujan masih gerimis di luar, aku meraihmu. Di cekungan punggungmu, tanganku tergelincir. Kusentuh lehermu, lunak. Dari balik kulitnya nadimu berdenyut. Di dalamnya, darah mengalir. Sunyi berkejaran di sana. Kau bergumam lagi.
"Tidak sayang, malam masih panjang." kataku. "Bersembunyilah."
Pagi nanti sejumlah headlines akan menyerbu. Aku ingin kita terperangkap di sini, dalam sekarat abadi ini, sebab hidup cuma setarikan nafas, dan kita cuma akan bisa berbahagia.
"Tidurlah," kataku. Kulitmu licin, dan tiap kali aku menyusurinya, hidup menguar dari tubuhmu, bergelombang; dimintanya engkau menanggunggkannya, dari sepi ke sepi, aku tahu.
Tapi tidak malam ini. Di bawah selimut, kita telanjang, seperti manusia pertama yang tidak mengenal pengetahuan, dan Tuhan seperaihan tangan dari adaku dan adamu. Semesta baru saja diciptakan, kau cium baunya, mengambang di luar sana. Kita tidak ingin perduli.
Di atas pahaku, kakimu menindihku. Kurasakan selangkanganmu di sana. Lembab, dan dalam setarikan nafas, aku akan tahu di situ menguar bau ludahku. Dalam gelap kita saling menjilat, karena kau tahu kita tidak abadi.
Ingin, ingin sekali aku menarikmu dari sana, dari tubuhmu yang tidur, untuk kemudian kau kenakan tubuhku, merasakannya. Aku ingin kau menjadi diriku, dalam dekat ini, memelukmu yang lelap. Dan akan kuajukan sebuah pertanyaan, "Apakah ia bahagia? Lihatlah, nafasnya teratur, kau bisa merasakan detak jantungnya, mendekatlah, cium ubun-ubunnya, kau baui rambutnya? Ia bahkan tidak mau melepaskan tubuhnya dari pelukanmu."
Akan ada sebuah perasaan bahagia yang ganjil menelusupimu. Mengembang seperti alam semesta, dari Penciptaan ke Kiamat, dan miliaran tahun adalah sekejapan mata. Akan ada jawaban untuk semua rahasia, yang akan menindihmu, sampai kau kelu, sebelum akhirnya meledak, sebab kau tidak akan mampu menyampaikannya padaku. Seperti Musa yang tak juga siuman di Bukit Sinai. Rahasia itu, bukankah tak tertahankan jawabannya, pun bila kau mampu memahaminya?
Di bawah rambutnya, kulitnya berwarna putih. Kau akan tersesat di sana. Setelah tersesat kau akan memanggil-manggil namanya, memintanya untuk membawamu pulang. Dan dia akan turun dari langit sebagai seekor bangau. Dan kau akan terbang bersamanya dalam gendongan di paruhnya, sebagai bayi. Dan dibawanya kau mengatasi keberadaanmu. Dan dibenamkannya kau dalam lembab hutannya, disusuinya kau dengan putingnya yang kerikil; kau akan menggigitnya keras-keras, sebelum ia melenguh. Dan dalam teriakan terakhir, dalam satu sentakan di selangkangannya, ia akan berdenyut cepat, melahirkanmu. Lalu kau akan menangis begitu saja seakan tanpa sebab, karen akau tidak ingin dilahirkan. Karena kau ingin terus berada di dalamnya. Karena kau adalah
anak cucu Adam, yang menangis jua di Canaan, setelah pengetahuan membuangnya dari surga. Dan dalam kapar, kau rasakan itu, keberadaanmu yang penuh sekaligus terasing, mengambang mengatasi dunia yang perawan di matamu, terhampar di luar tubuhmu. Aku tahu.
Dalam tidurmu, tahukah, aku berbisik padamu? "Setelah sejumlah teriakan tertahan dan ledakan, Mbak sayang, kita akan mengalami kematian-kematian kecil. Dengan demikian kita tahu, hidup ini berharga untuk dijalani, pun bila ia adalah sebuah kutukan."
Hujan masih gerismis di seberang jendela. Di sini, kita bersembunyi, dalam sekarat abadi.
***
Apa yang akan aku lakukan padamu, ketika pertama kali kita akan bertemu lagi?
Kulihat kau duduk di sana, di bangku fiber itu, keras, dingin , berwarna plastik. Dari jauh, aku akan sudah mencium baumu. Di tubuhku, melekat tujuh ratus kilometer pencarianku, bau besi layu, debu, keringat, debar jantungku. Di dadaku, kerinduanku. Di seberang pagar, Monas, tegak di atas Indonesia Raya yang terus menerus murung.
Kau seperti Jakarta. Bersolek terus menerus dan tak kunjung bahagia.
Aku akan menyapamu, mungkin dengan gugup, barangkali juga degup; dalam genggamanmu, kau tahu dalam diriku ada yang terus bersiap untuk meletup.
Lalu, Jakarta akan menenggelamkan kita. Di dalam taxi tangan kita bergenggaman, hatimu yang rusuh, sebab kau tahu barangkali tiap kelokan tengah mengawasimu. Di balik jendela, terpisah dari udara AC, Jakarta menggeram dan terengah; kemana, dimana, kemana Jakarta akan menyembunyikan kita?
Ingin ku bawa kau pergi dari sana, dari reruntuhan itu; di bawah lampunya yang gemerlap kau tidak berbahagia. Pergi, pergilah dari sana. Bersamaku kita putari bumi, seperti Columbus yang bertaruh dengan sebutir telur. Kita manusia pertama di muka bumi. Kau adalah istriku, Hawa, dan langit masih terus saja melengkung. Kau tahu, seharusnya kita tidak berada di sini. Kita pergi dari sini, ke tempat burung-burung bercakap, dan tak ada yang terjadi di luar lapar dan birahi.
Di bawah Pancoran, hatiku ngungun. Laki-laki gagah dan tegap itu, pada siapakah api yang nyala di tangannya itu hendak menerangi? Meluncur di jalan tol, menggenggam tanganmu, membaui ubun-ubunmu, dadamu yang lunak, tubuhmu yang lembut, kusapa Jakarta. Jakarta yang kubenci, Jakarta yang menyembunyikanmu. Jakarta yang menyembunyikan kita. Di bawah ketiaknya orang-orang berkerumun untuk hidup yang terlalu berlendir untuk dibela; Jakarta, Kramat Sentiong, Stasiun Tanah Abang, Tanjung Priok, Bekasi, di sana kita akan bercinta.
Aku tidak ingin kau hamil. Aku ingin menghamilimu di Tambi, di bawah perdu teh, tidak di sana. Aku ingin kau hamil, ketika kita bercinta di rerumputan, di semak-semak seperti binatang tak jauh dari belibis yang berenangan, di Ranu Kumbolo. Di rumahku kelak, tempat dua ekor koki berenangan di akurium dan hujan turun di luar. Tidak, tidak di Jakarta. Marilah kita menipu kota yang bangsat ini, kota yang terus menerus berdandan namun tak kunjung bahagia.
Perempuan-perempuan semakin banyak kutemui kau, semakin aku merasa sendiri.
Di manakah keabadian cintaku? Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, kalau kubenamkan wajahku di dadamu? Sebab tak mampu kutatap putingmu di mana dari sana menetes susu yang memberiku kehidupan. Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, bahwa tanpamu, siapakah aku di dataran keyakinan ini? Kau pahamikah ketakutanku, perempuan, bahwa di hadapanmu, aku berubah sebagai bayi, dan sebagai bayi aku tak hendak bersedia terlahir, seandainya saja bisa ku tawar? Bahwa disini, diriku, seluruh kekuatanku, kesombonganku, hidupku luruh, sebab kau perempuan, kau simpan jalan pulangku, di selangkanganmu?
Dalam birahi, kehidupan dan kematian bersatu. Dalam birahi, kau dan aku cabar seperti kabut. Dalam birahi, aku lenyap dalam dirimu. Maka perempuan, susui aku lagi .Biar kusesap habis dirimu, sebab dinamakanNya kau Hawa, lantaran kau adalah ibu dari segala kehidupan.
Denganmu, Mbak sayang, aku ngungun oleh cemas asali ini. Denganmu, Mbak, kubiarkan ia menipuku. Sebab dalam benamku di tubuhmu, aku akan berteriak, sebagaimana ceracau Adam oleh langit yang tanpa jawaban. Dan usai aku tumpah, Mbak, ingatkan aku untuk pulang. Sebab hidup belum lagi usai untuk dijalani. Sebab kau adalah istri seseorang. Sebab kita tidak berdosa, dan suatu ketika kelak kita tidak akan lagi harus bersembunyi. Kita akan bercinta di manapun, sebab dengan kesungguhan hati, kita akui kecemasan kita akan yang tak abadi itu. Dan hidup, ah, adalah kesempatan buatku untuk menciummu berpanjang-panjang.
Maka, Mbak, temui aku di stasiun Gambir, lalu kita susun kembali kemuakkan kita akan dusta kotamu, dan hidup kita dalam birahi, hingga terbakar , hangus dalam bahagia.
"Pulanglah ….dan jangan pernah untuk melihat kebelakang….dimana pernah ada kita". Tapi kau malah memintaku demikian. Mataku berkaca. Masih kugenggam erat tanganmu di atas meja, di sebuah rumah makan, di depan toko buku yang selalu menautkan hati kita melalui kesukaanmu itu. Cuma itu tempat kita.
"Tetaplah di Jogja, banyak hal yang bisa kau lakukan di sana. Itulah tempatmu,…"
"Tidak, Mbak, tempatku di sampingmu, kelak aku akan sanggup membawamu dari laki-laki itu."
"Tidak ada masa depanmu denganku, tolong, lupakan aku."
"Tapi kau tidak bahagia, kau disakitinya terus menerus,sepanjang waktu, dan aku tidak sanggup melihat itu."
"Bagaimanpun juga dia masih suamiku, apa yang kita lakukan adalah suatu kesalahan."
"Terlambat kau bilang itu sekarang, Mbak, Cuma kau tempatku pulang."
Persetan dengan laki-laki itu, dia pun mengkhianatimu, kenapa dia tidak menceraikanmu saja? Aku membencinya, juga kau atas nama cintaku. Aku mengutuk dalam hati.
Semua itu kemudian menjadi pembicaraan kita yang terakhir. Tak ada yang lebih kuat tersisa di ingatanku selain lebam di matamu, dan kau biarkan tangan laki-laki itu terus memperlakukanmu demikian. Maka aku pulang, kembali menjauh tujuh ratus kilometer darimu seperti sebelum semua dimulai.
Saat ketika kau tidak mengijinkanku menangis sendirian,
aku akan mengingatnya. Apapun yang akan kita tempuh…
You are the most precious thing ever happened in my life
Sender: mbak
+ 62812xxxxx
Ah Mbak, rupanya cintaku belum cukup besar untukmu.
Send.Klik.
Pending.
******
Bekasi, (sekian waktu yang lampau)
dimuat dalam buku kumcerku "Perempuan Di Balik Kabut"
" Menepilah…!"
Sebelah tanganmu menutup wajah, ketika darah terpercik dari kerumunan. Sebelah lagi kau biarkan kuraih untuk menepi.
"Tidak seharusnya dia diperlakukan begitu…dia hanya pencopet kecil…" suaramu merintih.
Sungguh aku yang terkapar, kau curi semua rasa di dalam hatiku dengan bibir gemetarmu, wajah pucatmu terus menerus menggantung di pelupuk mata. Kau bangkitkan aku berkali-kali.
Kau bilang kau pernah membenci kota ini, bahkan mungkin masih tersisa itu di dalam hatimu. Tapi sesuatu hal membawamu kemari, sendiri, dan pertemuan tak terduga ini mencipta banyak hal diluar kuasaku.
Kau cuma bergumam, dengan kalimat yang sulit kumengerti maknanya, bahwa alur hidupmu berubah di kota ini. Kota yang berpakaian sangat santun ini sanggup mencabik habis seluruh lorong nafasmu. Kau membenci tempatku menatap bintang sepanjang malam. Tapi disebaliknya, kau duduk bersebelahan denganku, cuma ini caramu mencintai rasa sakitmu, kau bilang begitu.
Tapi aku tidak cukup punya waktu untuk berusaha memahamimu, pun untuk memahami ledakan-ledakan dari suram di dalam sini. Aku berharap sedikit saja cahaya dari mendung di atas langit rumahku, tapi kau memberi banyak, lebih dari bulan yang sengaja purnama. Di usia hampir tiga puluhku ini, percayakah kau jika ku katakan bahwa cinta pertama kali datang untukku?
Aku selalu berharap kau percaya geletar pertama yang bangkit sebagai pengetahuan, ini adalah sesuatu yang kita sebuat cinta. Dan kau yang mebawanya ke rumahku, aku melihat geletar dimatamu yang tidak sependapat denganku.
"Apa artinya,." katamu. Tidak memberikan makna apa-apa dalam hidup, apakah dia datang yang pertama atau kesekian. Bagimu itu hanya dongeng-dongeng kepedihan yang terus menerus diturun temurunkan. Kenangan yang memaksakan diri untuk mencipta rasa bahagia bagi orang-orang yang merasa kehilangan.
Ah, tidak, aku tidak ingin membuat deretan kenangan di bumi ini tentang sebuah kisah cinta pertama. Memalukan, kita berdebat di rumput rumahku hanya karena sebuah cinta yang datang pertama kali. Tapi jika kau ijinkan aku bersumpah, aku ingin membelah langit dengan semburat dari matamu, sinar itu tentu akan sanggup, seperti ia telah membelah dadaku dan meninggalkan bongkahan besar untuk selalu kusimpan.
***
Kau mulai menyibakkan selubung kelabumu dengan sebuah kisah seperti hujan yang sangat sedikit, tentang kebencianmu yang membuatmu selalu merasa terdampar di kota ini sekaligus membuatmu ingin kembali dan kembali, meski tanpa kekuatan.
Kala itu, berbaring dalam telanjang di tengah jerami kering, Jogja, memanggilmu "perawan". Tapi engkau bukan Maria, dan juga bukan bayimu (yang tak sempat lahir) adalah Jesus.
"Tapi telah kuberikan cintaku seutuhnya!" sergahmu.
Tetap saja, sejarah mengancingkan celananya dan berpaling. Maka dengan pedih di selangkanganmu kau teruskan hidupmu. Kota itu pun bangkit dari tidur ayamnya dan mencegahmu berpamitan.
Kau lalu memang menyelinap darinya sambil terus menyusun kiat yang lebih nyaman untuk berselingkuh dengan dirimu sendiri, sebab semua kota cuma hamparan lendir bagimu. Kau terus berjalan karenanya, sampai kemudian kau temui laki-laki lain itu, yang telapak tangannya berlubang. Dan selain alasan penyaliban atas dirinya sendiri, ditempuhnya sekarat untuk ia sampaikan pesan ini : Bahwa Engkau tak berdosa Bahwa kota itu, yang adalah kota ini, tetap memanggilmu "perawan!"Kau menyusut air matamu perlahan.
Tapi ternyata musim berdusta tak bertahan lama, kau terkoyak lagi, oleh sebuah penuntutan yang tak bisa mengadili dengan adil. Kau tetap saja seorang perempuan yang tidak sebening embun ketika matahari mulai terbangun walau hanya kota ini yang tetap memanggilmu perawan.
Kau ciptakan sungai dan senja, di sebalik kenanganmu yang sarat oleh siksa, juga di telapak tanganmu. Warna jingga keunguan kau semburatkan di ujung jari. Jika makna alirku serupa batu hitam di dasar berlumut, hanya senjamu yang dapat menghapus warna laut. Abadikan ia dalam remasan tanganmu. Dan kapal-kapal akan terselip di rambutku. Badai akan tercipta dari helai-helai gairah yang berguguran. Mengalir, mengalirlah kata-katamu di sungai mu. Senja merah yang sangat kusuka. Tanganmu kekal meremas punggunggku.
Lalu kau menangis…..
Dengarlah perempuan yang kutemui dalam separuh perjalananku, aku adalah batu hitam yang diam itu. Sebermula adalah wujud untuk kemudian menjadi ada. Dari ada lalu terbit kesedihan, dan pada kesedihan hinggap kehidupan. Bersamanya, hinggap pula engkau. Maka cuaca telah mempertemukan kita. Dan senja yang kau ciptakan memperlembut kemarau, menaburkan embun dan menumbuhkanmu. Akarmu lembut menggemburkanku. Lalu dalam musim, kau mengikisku, butir demi butir, tanpa aduh, tanpa keluh.
Kau telah menghidupkan aku dalam urai. Untuk kemudian larut sebagai gembur, tempat di atasnya kau beranak pinak, menghampar hijau tengadah menentang matahari. Bersediakah kau menikah denganku nanti?
Kau cuma menangis….(lagi)
Sementara putingmu bergeser di punggungku, aku bercerita bahwa sebatang selokan ini Rajaku yang bikin. Ketika Opak dan Progo bertemu, maka Mataram akan menjadi rahim bagi kelanggengan. Ketika kemudian sungai darahmu dan sungai darahku menyatu tak lama kemudian, tidakkah gagasan tentang keabadian Mataram itu begitu syahwati? Tak kau jawab tanyaku.
Matamu maut yang padam menatapku, dan cengkeraman kukumu di punggunggku…Ah..keabadian adalah sedetik sebelum kau tertelungkup, sungai hidupmu mengalir, sungai hidupku mengalir, dalam gelimang cahaya bulan di permukaan selokan Mataram.
Kau telah menemukanku, yang tersesat dalam kabut. Ketika kupanggil namaku, tapi cuma gaungnya sendiri. Lalu hujan turun, lagi, bertahun kemudian. Masih saja tak ada siapapun. Cuma sepotong sajak yang menegaskan aduhku. Hujan turun di rumput. Ada juga hujan untukku, dan Nuh. Tapi tak akan aku bersamanya, sebab bahkan belibis pun berpasangan di danau itu. Siapa gerangan aku, laki-laki, di padang ini, di Timur Sorga, tanpa Hawa?
Ingin kusebut engkau ibuku, yang telah memberiku koin, untuk membuatku menempuh level berikutnya. Kau telah membuatku terus menerus merasa berharga, sebab koin-koin membuat pertempuran terus ada, dan akulah pemenangnya. Meski bila tidak, kau selalu memberiku nafas, seperti koin yang terus selalu ada untuk pertarungan berikutnya.
Ingin ku sebut kau adalah ibuku, yang dari putingmu terus menggelinding koin-koin berikutnya, gairah hidupku, rasa adaku. Kau yang telah menemukanku! Tidak sekedar sebuah cinta baru tumbuh di hati yang berkarat. Kau menarikku dari tempatku tinggal, membuka mata hati untuk berusaha melihat bahwa jalan ini tidak seburuk yang kukira. Patahan-patahan semangat kau susun, seperti menjahit perca demi perca. Kau mencipta aku, wahai perempuan. Lebih dari sekedar jasadmu yang terbangun dari tulang rusukku. Ah, karena itukah yang membuatku lemah…sementara kau tidak perempuan, tak ada yang mengurangi rusukmu.
Kupikir kita telah menggenggam harapan, ketika kita menautkan apa yang disebut cinta. Terlambatkah itu menyerbuku? Lalu kaupun berkemas, sebelum mengakhirinya dengan sebuah selamat tinggal yang ganjil. Tapi kereta selalu tak mau menunggu, meskipun ia selalu bisa saja berangkat telat, seperti semua kekasih yang mengkhianatimu.Hingga malam itu, dalam lengking yang terdengar seperti peluit terakhir, malam menelanmu bulat-bulat, dengan suara gemuruh yang masih saja bergema sebagai separo mimpi separo jaga hingga dua puluh tujuh purnama kemudian.
Aku mengenangmu sebagai suara gemuruh yang hilang di ujung stasiun, mengingatnya lagi dan lagi, bertalu-talu dalam nadiku. Hingga kemudian, ia menyatu sebagai degup jantungku. Demikianlah engkau tinggal dalam diriku, jauh sesudah semua pengkhianatan yang paling pedih dilupakan orang, dan bahkan tidak bisa kueja lagi sejarahmu sebagai kata-kata. Engkau tinggal di sekelilingku sebagai cuaca yang memerangkapku dari musim ke musim.
Tapi pun aku tahu, kau mengambang juga di langit kotamu. Memerangkap sekian laki-laki lain dalam cuaca. Aku tahu. Aku tahu. Pengkhianatan telah menjadikanmu begitu lihai mengemas kegetiran. Dan kereta malam terakhir itu telah benar-benar merampasmu dari heningku yang sudah mulai bingar. Kau selimuti engganmu dengan senyum , dari sebalik jendelamu kutanggap keberatan itu. Tangan yang dipaksa untuk melambai tanpa gerak, melekat. Aku berlari, coba menyusulmu, mengiringi lajunya. Kau terampas, aku terkapar, aku harap ini hanya sejenak. Sekedipan mata. Kelak aku ingin kita bertemu lagi.
Kau tahu, di seberang pengkhianatan, tidak ada lagi yang cukup pedih untuk menjadi sebuah roman yang mengharukan, pun juga tidak celotehan tolol separo-mimpi-separo jaga ini. Kelak, aku akan cuma jadi laki-laki kesekian dalam hidupmu. Laki-laki kesekian yang tidak penting lagi untuk mencintaimu atau mengkhianatimu. Tapi aku mengingatmu, sebagai gemuruh yang lenyap di ujung stasiun.
Satu-satunya ingatan yang diijinkan kumiliki, sebelum membeku sebagai sebongkah batu, yang cuma bisa merasakan kesunyian, tapi tak bisa menamainya. Ya, aku tak bisa menamaimu. Aku merasakanmu, mengingatmu, tapi tak bisa kunamai kenanganku.
Kelak, perempuan, bila tiba saatnya, aku akan menemuimu, setelah kusesap lagi Buah Pengetahuan sekali lagi, terkutuk untuk kedua kalinya, terlempar dari diam ini, mencarimu di muka bumi, terperangkap di bawah kolong langit. Sebab, perempuan, sebab it is you that invented me.
******
Ah….Dimanakah kau, Mbak?
Betapa tololnya aku, setelah habis hembusan rokokku berbatang-batang baru kusadari kau begitu jauh dariku. Berapa jarak kita, Mbak? Ratusan kilometer ini menjamahku dari tenang di sisimu. Kau ada di jarak itu, dalam sebuah rumah, dimana seorang laki-laki menjaga pintunya, dan di kakinya kau bersimpuh, membasuhnya. Mungkin bukan, kau adalah putri itu, yang selendang putihnya melambai oleh angin di pucuk menara, dengan naga melingkar di jenjangnya, dengan mantra mengambang di gerbangnya. Di sana, aku tahu, seorang nenek sihir menjelma laba-laba tua yang sarangnya memenjaramu.
Tracy Chapman di layar, menggantung di depan stage. Di atasku, langit menyingkap, bintang-bintang, ah. Sebatang lilin bertahan dari gerimis di sebuah cekungan, mencegahmu untuk tidak terperosok di sana, lalu bangku-bangku , dan kursi, music itu, gadis –gadis bak boneka keramik itu, sejumlah pasangan yang bergeremang dalam gelap. Kupikir kopi ini terlalu pahit, mungkin aku membutuhkan tambahan gula. Ketika waitress itu mendekat, ia mendekatkan telinganya ke mulutku, "Apakah saya bisa minta tambahan gula lagi?"
Kupikir aku adalah seorang pengembara, menyalakan unggunan api di seberang jendelamu. Kulihat kau berdandan, nun di atas sana, dan selendang itu masih saja melambai oleh angin. Ketika kusesap kopiku, dari balik lidah api itu, kesedihan menyerbu dengan cara yang sangat menyakitkan; untuk siapakah gerangan, Her majesti, engkau berdandan? Sungguh angin begitu jahat di luar sini. Dan sunyi ini merubung tak tertahankan. Pun langit tetap saja melengkung tanpa jawaban. Kenapa kita tidak bercakap saja, berdiang dengan kata-kata ; mungkin tidak, mungkin cuma bertatapan, atau bercinta begitu saja, seperti sepasang serangga.
Lalu, sejumlah permaafan, atas jarak itu, laki-laki itu, nenek sihir itu, naga yang melingkar itu, mantra itu, menara itu, adaku dan adaku, yang tak bersisian. Ketika aku mendongak, kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali.
Seseorang memanggil namaku, "Maukah kau memberi pengantar untuk pertunjukan kita malam ini?"
Menempuh meja-meja itu, gerimis membungkusku, dan di bawah lampu aku tersenyum pada penonton yang tak kukenal dan berkerumun dalam remang. Ia mati muda, kataku, seperti Chairil Anwar, Soe Hok Gie, atau Nike Ardilla. Kerumunan itu tidak menjawab, aku tahu, aku bicara untuk diriku sendiri, sebab aku adalah laki-laki di bawah sorot lampu.
Aku berharap kau ada di sana, meskipun tak kulihat kau dalam gelap. Aku berharap kau menungguku, setelah aku turun dari panggung, menempuh meja-meja, pasangan yang bergenggaman, dentum musik dan sorot lampu. Aku berharap kau menungguku, untuk saling berbisik lagi, dan menjadikanku laki-laki yang tidak bicara pada dirinya sendiri.
Dalam benakku, kutemukan kau menatapku. Matahari sudah tenggelam lama sekali. Hallo, can I call You, Mbak? Tengah malam ini, kutulis sebuah surat panjang untukmu.
Aku belum bisa terlelap. Kamu sedang apa?
Sender: mbak
+ 6281284XXXXX
Boleh aku menelponmu, mbak? Sebentar saja.
Send.Klik
Delivered
Tidak perlu! Dia memang tidak pulang lagi malam ini.
Aku hanya ingin tahu kamu baik-baik saja.
Irit-irit pulsamu. Selamat tidur ya?
Sender: mbak
+ 6281284XXXXX
***
Dalam tidurmu kau bergumam. Dan ketika kusadari bahwa hujan masih gerimis di luar, aku meraihmu. Di cekungan punggungmu, tanganku tergelincir. Kusentuh lehermu, lunak. Dari balik kulitnya nadimu berdenyut. Di dalamnya, darah mengalir. Sunyi berkejaran di sana. Kau bergumam lagi.
"Tidak sayang, malam masih panjang." kataku. "Bersembunyilah."
Pagi nanti sejumlah headlines akan menyerbu. Aku ingin kita terperangkap di sini, dalam sekarat abadi ini, sebab hidup cuma setarikan nafas, dan kita cuma akan bisa berbahagia.
"Tidurlah," kataku. Kulitmu licin, dan tiap kali aku menyusurinya, hidup menguar dari tubuhmu, bergelombang; dimintanya engkau menanggunggkannya, dari sepi ke sepi, aku tahu.
Tapi tidak malam ini. Di bawah selimut, kita telanjang, seperti manusia pertama yang tidak mengenal pengetahuan, dan Tuhan seperaihan tangan dari adaku dan adamu. Semesta baru saja diciptakan, kau cium baunya, mengambang di luar sana. Kita tidak ingin perduli.
Di atas pahaku, kakimu menindihku. Kurasakan selangkanganmu di sana. Lembab, dan dalam setarikan nafas, aku akan tahu di situ menguar bau ludahku. Dalam gelap kita saling menjilat, karena kau tahu kita tidak abadi.
Ingin, ingin sekali aku menarikmu dari sana, dari tubuhmu yang tidur, untuk kemudian kau kenakan tubuhku, merasakannya. Aku ingin kau menjadi diriku, dalam dekat ini, memelukmu yang lelap. Dan akan kuajukan sebuah pertanyaan, "Apakah ia bahagia? Lihatlah, nafasnya teratur, kau bisa merasakan detak jantungnya, mendekatlah, cium ubun-ubunnya, kau baui rambutnya? Ia bahkan tidak mau melepaskan tubuhnya dari pelukanmu."
Akan ada sebuah perasaan bahagia yang ganjil menelusupimu. Mengembang seperti alam semesta, dari Penciptaan ke Kiamat, dan miliaran tahun adalah sekejapan mata. Akan ada jawaban untuk semua rahasia, yang akan menindihmu, sampai kau kelu, sebelum akhirnya meledak, sebab kau tidak akan mampu menyampaikannya padaku. Seperti Musa yang tak juga siuman di Bukit Sinai. Rahasia itu, bukankah tak tertahankan jawabannya, pun bila kau mampu memahaminya?
Di bawah rambutnya, kulitnya berwarna putih. Kau akan tersesat di sana. Setelah tersesat kau akan memanggil-manggil namanya, memintanya untuk membawamu pulang. Dan dia akan turun dari langit sebagai seekor bangau. Dan kau akan terbang bersamanya dalam gendongan di paruhnya, sebagai bayi. Dan dibawanya kau mengatasi keberadaanmu. Dan dibenamkannya kau dalam lembab hutannya, disusuinya kau dengan putingnya yang kerikil; kau akan menggigitnya keras-keras, sebelum ia melenguh. Dan dalam teriakan terakhir, dalam satu sentakan di selangkangannya, ia akan berdenyut cepat, melahirkanmu. Lalu kau akan menangis begitu saja seakan tanpa sebab, karen akau tidak ingin dilahirkan. Karena kau ingin terus berada di dalamnya. Karena kau adalah
anak cucu Adam, yang menangis jua di Canaan, setelah pengetahuan membuangnya dari surga. Dan dalam kapar, kau rasakan itu, keberadaanmu yang penuh sekaligus terasing, mengambang mengatasi dunia yang perawan di matamu, terhampar di luar tubuhmu. Aku tahu.
Dalam tidurmu, tahukah, aku berbisik padamu? "Setelah sejumlah teriakan tertahan dan ledakan, Mbak sayang, kita akan mengalami kematian-kematian kecil. Dengan demikian kita tahu, hidup ini berharga untuk dijalani, pun bila ia adalah sebuah kutukan."
Hujan masih gerismis di seberang jendela. Di sini, kita bersembunyi, dalam sekarat abadi.
***
Apa yang akan aku lakukan padamu, ketika pertama kali kita akan bertemu lagi?
Kulihat kau duduk di sana, di bangku fiber itu, keras, dingin , berwarna plastik. Dari jauh, aku akan sudah mencium baumu. Di tubuhku, melekat tujuh ratus kilometer pencarianku, bau besi layu, debu, keringat, debar jantungku. Di dadaku, kerinduanku. Di seberang pagar, Monas, tegak di atas Indonesia Raya yang terus menerus murung.
Kau seperti Jakarta. Bersolek terus menerus dan tak kunjung bahagia.
Aku akan menyapamu, mungkin dengan gugup, barangkali juga degup; dalam genggamanmu, kau tahu dalam diriku ada yang terus bersiap untuk meletup.
Lalu, Jakarta akan menenggelamkan kita. Di dalam taxi tangan kita bergenggaman, hatimu yang rusuh, sebab kau tahu barangkali tiap kelokan tengah mengawasimu. Di balik jendela, terpisah dari udara AC, Jakarta menggeram dan terengah; kemana, dimana, kemana Jakarta akan menyembunyikan kita?
Ingin ku bawa kau pergi dari sana, dari reruntuhan itu; di bawah lampunya yang gemerlap kau tidak berbahagia. Pergi, pergilah dari sana. Bersamaku kita putari bumi, seperti Columbus yang bertaruh dengan sebutir telur. Kita manusia pertama di muka bumi. Kau adalah istriku, Hawa, dan langit masih terus saja melengkung. Kau tahu, seharusnya kita tidak berada di sini. Kita pergi dari sini, ke tempat burung-burung bercakap, dan tak ada yang terjadi di luar lapar dan birahi.
Di bawah Pancoran, hatiku ngungun. Laki-laki gagah dan tegap itu, pada siapakah api yang nyala di tangannya itu hendak menerangi? Meluncur di jalan tol, menggenggam tanganmu, membaui ubun-ubunmu, dadamu yang lunak, tubuhmu yang lembut, kusapa Jakarta. Jakarta yang kubenci, Jakarta yang menyembunyikanmu. Jakarta yang menyembunyikan kita. Di bawah ketiaknya orang-orang berkerumun untuk hidup yang terlalu berlendir untuk dibela; Jakarta, Kramat Sentiong, Stasiun Tanah Abang, Tanjung Priok, Bekasi, di sana kita akan bercinta.
Aku tidak ingin kau hamil. Aku ingin menghamilimu di Tambi, di bawah perdu teh, tidak di sana. Aku ingin kau hamil, ketika kita bercinta di rerumputan, di semak-semak seperti binatang tak jauh dari belibis yang berenangan, di Ranu Kumbolo. Di rumahku kelak, tempat dua ekor koki berenangan di akurium dan hujan turun di luar. Tidak, tidak di Jakarta. Marilah kita menipu kota yang bangsat ini, kota yang terus menerus berdandan namun tak kunjung bahagia.
Perempuan-perempuan semakin banyak kutemui kau, semakin aku merasa sendiri.
Di manakah keabadian cintaku? Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, kalau kubenamkan wajahku di dadamu? Sebab tak mampu kutatap putingmu di mana dari sana menetes susu yang memberiku kehidupan. Kau pahamikah kecemasanku, perempuan, bahwa tanpamu, siapakah aku di dataran keyakinan ini? Kau pahamikah ketakutanku, perempuan, bahwa di hadapanmu, aku berubah sebagai bayi, dan sebagai bayi aku tak hendak bersedia terlahir, seandainya saja bisa ku tawar? Bahwa disini, diriku, seluruh kekuatanku, kesombonganku, hidupku luruh, sebab kau perempuan, kau simpan jalan pulangku, di selangkanganmu?
Dalam birahi, kehidupan dan kematian bersatu. Dalam birahi, kau dan aku cabar seperti kabut. Dalam birahi, aku lenyap dalam dirimu. Maka perempuan, susui aku lagi .Biar kusesap habis dirimu, sebab dinamakanNya kau Hawa, lantaran kau adalah ibu dari segala kehidupan.
Denganmu, Mbak sayang, aku ngungun oleh cemas asali ini. Denganmu, Mbak, kubiarkan ia menipuku. Sebab dalam benamku di tubuhmu, aku akan berteriak, sebagaimana ceracau Adam oleh langit yang tanpa jawaban. Dan usai aku tumpah, Mbak, ingatkan aku untuk pulang. Sebab hidup belum lagi usai untuk dijalani. Sebab kau adalah istri seseorang. Sebab kita tidak berdosa, dan suatu ketika kelak kita tidak akan lagi harus bersembunyi. Kita akan bercinta di manapun, sebab dengan kesungguhan hati, kita akui kecemasan kita akan yang tak abadi itu. Dan hidup, ah, adalah kesempatan buatku untuk menciummu berpanjang-panjang.
Maka, Mbak, temui aku di stasiun Gambir, lalu kita susun kembali kemuakkan kita akan dusta kotamu, dan hidup kita dalam birahi, hingga terbakar , hangus dalam bahagia.
"Pulanglah ….dan jangan pernah untuk melihat kebelakang….dimana pernah ada kita". Tapi kau malah memintaku demikian. Mataku berkaca. Masih kugenggam erat tanganmu di atas meja, di sebuah rumah makan, di depan toko buku yang selalu menautkan hati kita melalui kesukaanmu itu. Cuma itu tempat kita.
"Tetaplah di Jogja, banyak hal yang bisa kau lakukan di sana. Itulah tempatmu,…"
"Tidak, Mbak, tempatku di sampingmu, kelak aku akan sanggup membawamu dari laki-laki itu."
"Tidak ada masa depanmu denganku, tolong, lupakan aku."
"Tapi kau tidak bahagia, kau disakitinya terus menerus,sepanjang waktu, dan aku tidak sanggup melihat itu."
"Bagaimanpun juga dia masih suamiku, apa yang kita lakukan adalah suatu kesalahan."
"Terlambat kau bilang itu sekarang, Mbak, Cuma kau tempatku pulang."
Persetan dengan laki-laki itu, dia pun mengkhianatimu, kenapa dia tidak menceraikanmu saja? Aku membencinya, juga kau atas nama cintaku. Aku mengutuk dalam hati.
Semua itu kemudian menjadi pembicaraan kita yang terakhir. Tak ada yang lebih kuat tersisa di ingatanku selain lebam di matamu, dan kau biarkan tangan laki-laki itu terus memperlakukanmu demikian. Maka aku pulang, kembali menjauh tujuh ratus kilometer darimu seperti sebelum semua dimulai.
Saat ketika kau tidak mengijinkanku menangis sendirian,
aku akan mengingatnya. Apapun yang akan kita tempuh…
You are the most precious thing ever happened in my life
Sender: mbak
+ 62812xxxxx
Ah Mbak, rupanya cintaku belum cukup besar untukmu.
Send.Klik.
Pending.
******
Bekasi, (sekian waktu yang lampau)
dimuat dalam buku kumcerku "Perempuan Di Balik Kabut"
Rabu, 09 Mei 2012
Langit Sephia Berbingkai Jendela
Cuma ada debaran keras di dada, sekaligus bercerita tentang ketidakberdayaan. Kelelahan bertahun untuk terus menerus berusaha mempertahankan tahta di hati seseorang. Semestinya ia tidak sendirian di sini, menyapu permukaan ranjang berlapis sutra dengan betisnya yang putih dan jenjang. Dingin menyergap, membungkusnya, sedangkan ia setengah telanjang. Semestinya ia tidak kesepian di sini, karena kamar ini selalu hingar di penghujung minggu, bercinta sampai pagi, mencoba metode baru bersetubuh, meledak berkali-kali sampai ke puncak keyakinannya tersimpan di hati laki-laki pasangannya. Lalu sederet kecil berlian akan disematkan pada lehernya. Namun demi Tuhan, bukan itu lagi yang ia damba, laki-laki yang sepantasnya menjadi bapaknya itu menyemaikan cinta dan pengharapan lebih dari sekedar perempuan simpanan. Ia ingin dicinta, sebagaimana perempuan yang utuh.
Kini ia menatap cermin, keningnya basah oleh peluh, disapunya perlahan menyusuri leher lalu berhenti di dadanya yang masih saja bergantung indah, entah sudah berapa laki-laki yang pernah meningalkan jejak samar di sana selain seorang anaknya. Ada guratan sangat halus nyaris tak terlihat di ujung kedua matanya, namun masih saja tampak indah untuk gambaran seorang perempuan berusia di atas tiga puluh tahun. Cerlang matanya meredup, ada warna gelap di kantung matanya, wajahnya kusut, ah…ia terlalu banyak minum semalam. Namun hanya dari situ ia mendapatkan gelora, gairah untuk terus bertahan dan menikmati keutuhan cintanya pada laki-laki itu yang sering datang sebagai bayang-bayang dari pada kenyataan.
Tubuh putihnya yang setengah telanjang menggeser perlahan, meraih setumpuk surat yang belum lagi dibaca. Ia sudah tahu apa isinya tanpa perlu membukanya. Kabar tentang ayah ibunya yang sudah renta di kampung, bibinya, kakaknya, seorang anaknya, kemudian sederetan angka-angka yang mesti ia kirimkan untuk menghidupi semua orang tercinta itu. Perasaan nelangsa , kesepian dan kemarahan yang terpendam begitu rupa membuat ia tidak bersemangat untuk memikirkan siapapun. Mengapa ia biarkan dirinya terlanda damba cinta dan hangat seperti ini? Seharusnya tak perlu, hanya bikin siksa.
Sebelah kakinya bersila di atas kursi, g-stringnya merebak, sekali saja seakan tanpa sengaja ia usap belahan di antara dua pangkal pahanya, basah. Andai saja ia masih berhak menerima setiap pria yang menginginkannya, tentu tak perlu merasa kesepian. Banyak hal yang bisa membuatnya lupa akan pedihnya, paling tidak ia tidak akan pernah merasakan sungguh-sungguh sendirian. Walau mungkin semu.
Genap delapan minggu tanpa laki-laki itu, tanpa pertarungan bersimbah keringat, tanpa pergumulan yang disudahi dengan jeritan panjangnya. Bangsat betul! Laki-laki itu menyimpannya untuk dinikmati sendiri, juga disimpan untuk diasingkan, tak terjamah, tak tersentuh. Delapan kali minggu laki-laki itu mengingkari janjinya, tiada kabar, tiada pesan yang tertinggal. Semua sms yang ia kirimkan ber- report: pending. Hanya suara perempuan yang diatur secara otomatis menyambut suaranya. Halo…halo…. Aku lelah! Aku lelah hidup seperti ini. Nikahi aku saja atau lepaskan aku kembali ke tengah malam.
Untuk kesekian kali ia pandangi wajahnya di cermin, meraih sebatang rokok, membakarnya. Seperti iseng, ia mencore-coret wajahnya dengan kosmetik, berusaha terus menerus mengganti identitasnya. Ia melakukannya sambil terus merokok, tiap satu coretan ia berhenti, mengamati lekat-lekat wajah yang terpantul dari cermin. Siapa ini? Akukah? Seperti apa aku ini? Namun tiap kali ia berhenti dan memandang dirinya sendiri yang tertangkap hanya kepulan tipis asap rokok seperti tirai di hadapan wajahnya. Menangakap bayangan wajahnya sendiripun tak lagi bisa, dan ia tak perduli. Enyahlah kau perempuan malang di dalam cermin! Makin ia tebalkan asap itu, terus menerus hingga kamarnya putih kelabu, sampai ia terhenti sebab kepulan asap itu seperti jemari yang menyekik lehernya.
Ia menyeret langkahnya tanpa semangat, membungkuk meraih tas di kolong ranjang dan mengeluarkan sebuah handycam dari dalam tasnya. Kemudian ia memutarnya, di displaynya terlihat wajahnya sendiri, pada waktu yang lain.
DI LCD
(Ia duduk di atas ranjang, bersila, penuh telanjang, menjepit sebatang rokok yang belum dinyalakn di antara jemarinya)
Semua ini tentang kesedihanku, terperangkap di istana ini, berdandan, mematut-matut diri di cermin dengan lingerie yang selalu baru untuk menyita perhatianmu, berusaha kerasa melahap pengetauan bersetubuh dengan gaya baru untukmu. Namun, kita bukan suami-istri, aku hanya simpananmu….
(Tampak ia mengusap ujung dadanya dengan punggung tangannya)
Aku benci kenapa aku harus mengingat-ingat, kenapa aku tak boleh lupa bahwa aku hanya simpananmu. Dilarang keras bergandengan mesra denganmu di keramaian, tidak kau bawa di undangan teman-temanmu, kau hanya menyimpanku baik-baik di sini, tak boleh terjamah selain kau, mesti selalu segar dan merangsangmu. Setiap kali kau mau. Aku hanya ingin kau ada kali ini, lalu kita bercakap, agar kau tau ini real, rasa sakitku nyata.
( Ia tertunduk, mengusap pelan sudut matanya yang mulai basah)
Terdengar suara berdecit,ia menekan tombol fastforward tanpa melepaskan tombol play-nya. Lalu berhenti di sebuah gambar:
Di LCD
(Ia menyelipkan paha laki-laki berumur lima puluh lima tahun itu di pangkal antara dua kakinya yang mulus, keduanya penuh telanjang)
Aku kesepian, aku telah kehilangan banyak hal. Kau tidak pernah mengenal rasa kehilangan.
(Tangan laki-laki itu meremas dadanya, seakan gemas, tak habis-habis, kemudian tangan itu tinggal di putingnya)
Kau punya segalanya kini, manisku.
(Ia merapatkan tubuhnya , lebih dekat ke dada laki-laki itu)
Tapi aku tidak memilikimu.
(laki-laki itu sedikit gusar, ia meraih selimut, pejamkan mata, tak bersemangat)
Bukankah ku penuhi segala kebutuhanmu?
(Merajuk, ia lebih merapat lagi)
Kau berjanji menikahiku, kita adalah sepasang kekasih kan? Atau aku hanya simpananmu saja?
(Laki-laki itu lebih gusar lagi, menggeser tubuhnya agar menjauh)
Menikah? Kau setuju begini sajakan pada awalnya? Kenapa tiba-tiba minta dinikahi? Cobalah realistis, Elsya. Yang penting tidak ada wanita lain. Selain kau, hanya istriku. Aku tidak bisa menceraikannya, Elsya, itu tidak masuk akal. Ah, matikan kamera itu, aku tidak suka kau merekam!
(Segera ia membelakangi laki-laki itu, hatinya patah, bukan untuk merajuk)
Lebih baik aku kembali menyanyi di club, tak seorangpun memiliki aku , juga tak seorangpun yang kumiliki. Itu lebih adil.
(Laki-laki itu terkejut, tak menduga, cepat saja laki-laki itu meraih tubuhnya, menyibak selimut, meloncat ke atasnya kemudian menindihnya)
Tenang, manis. Jangan kembali ke club, baiklah, aku akan pikirkan hal ini. Kita akan menikah……maka jadilah pengantinku malam ini……
(kemudian dua tubuh itu saling bertindihan dan terguncang di balik selimut yang dibalutkan dan terdengar suara ranjang mewah yang seharusnya tidak berderit)
Ia menekan tombol stop dengan mata yang merah dan basah. Gambar itu sembilan minggu yang lalu, ia ambil sebelum laki-laki itu tak berkabar.
Kemudian ia bangkit lalu membuka jendela apartemennya, langit meredup dengan cakrawala bernuansa sephia, menantang gedung-gedung tinggi yang menyinarkan lampunya. Ah, seakan ia berdiri di tengah panggung, suara beat yang berdetak meruntuhkan jantung, suara-suara sintetik. Cahaya berwarna merkuri menerpa sebagian wajahnya. Cantik wajah itu cemerlang, namun matanya hampa. Tubuhnya seperti bidadari yang terluka, perlahan berubah menjadi seekor serangga yang siap membenturkan dirinya pada nyala yang panas.
Nyanyian itu memerangkapnya begitu rupa, ia mulai mengulang-ngulang sebuah bait, seperti meracau, seperti menjerit, seperti berteriak, tercekat berulang kali kemudian ia sungguh tercekik. Lalu ia jatuh di pinggiran ranjang dengan sengal napas dalam telungkup tubuhnya. Ia tampak begitu kesakitan.
Namun ia segera bangkit melupakan rasa sakitnya, melakukan ritual di depan cermin, sangat berhati-hati bagaikan sebuah upacara. Membubuhkan bedak penuh khidmat, sekali lagi ia terpenjara dalam perasaannya sendiri. Sambil bersenandung ia mengusap pelan wajahnya, lehernya dadanya, putting susunya. Ia berdiri, menari-nari, berputar, meliuk dengan sangat erotis. Ketika selesai lagunya dinyanyikan, ia kelelahan, terengah-engah seperti terpuaskan berkali-kali. Kembali ia menatap wajahnya di cermin yang selalu saja menjadi semakin asing, siapakah perempuan di cermin ini? Tak usah perduli, kepulkan saja asap rokokmu, tebalkan, agar kau tak lihat siapa ia.
Kau hanya perlu tidur panjang, Elsya. Perempuan malang, tidurlah agar berhenti juga kau rasakan deritamu. Dalam lelapmu nanti, kau akan terbebas dari segala nelangsa.
Ia meraih gaun putih berdada rendah, mengenakannya. Seketika tampil seorang perempuan matang yang begitu menawan, begitu berkelas, begitu anggun. Tapi perempuan ini nyata-nyata begitu rapuh, seperti gerabah. Sebenarnya ia tak ingin banyak hal, hanya ingin meraih cinta yang belum pernah ada dalam hidupnya. Tetapi yang tinggal adalah segerombolan serigala liar yang berkeliling di sekitarnya, siap menerkam dan menikmati cabikan tubuhnya. Serigala yang paling kejam adalah James, wajah pria itu muncul dengan tubuh binatang. James, pemilik club. Ia menyanyi di club sekaligus menjadi pemuas hasrat James, menyusul jadi santapan bagi serigala lain yang kelaparan, sahabat-sahabat dan tamu-tamu si pemilik club.
Lalu seseorang datang laksana penyelamat, menebusnya dari club setahun ini, menafkahi keluarganya, mengikatnya. Dan cinta datang kemudian, pada laki-laki yang telah beristri dan tidak mungkin dapat menikahinya atas dasar sebuah nama baik. Namun bila laki-laki itu beranjak darinya, maka sebagian dirinya akan mati.
Ia meletakkan kamera pada tripodnya, duduk bersila di atas ranjang berhadapan dengan kameranya. Gaun putih menutup lembut seluruh tubuh mulusnya, hanya pucuk dadanya yang mengeras mengintip dari sebalik gaunnya. Wajahnya pucat, namun sangat pasrah, berjuta gurat lelah akan pedih masih jelas terlukis, takkan terhapus.
Di viewfinder kamera itu, terlihat ia menggenggam remote. Lalu ia mulai merekam:
“Ini adalah kesedihanku yang kesekian, ketika tak juga aku dapat bangkit dan membuat hatiku menjadi lebih kuat. Aku terlalu letih untuk mengarungi hidup ini selanjutnya. Kepada yang mencintaiku, maafkan aku karena rapuhku, karena dendamku pada masa lalu yang melukaiku, juga karena cintaku pada seorang laki-laki yang tak dapat kutanggungkan sendirian. Hatiku tak cukup luas untuk menampung cinta ini, aku tak bisa hidup dengan laki-laki tanpa cinta pun tak bisa hidup tanpanya. Selalu saja cintaku tumbuh di tempat yang salah. Sungguh aku patah lagi. Maafkan atas salahku ini, yang kusadari namun sangat terlambat.”
Kamera itu masih menangkap gambar saat ia menenggak air putih benyak-banyak tiap kali setelah menjejalkan sejumlah dari puluhan butir obat tidur ke mulutnya, sampai botol itu kosong. Lalu mengucapkan sesuatu sebelum merebahkan dirinya dengan lembut di atas ranjang dan memejamkan matanya. Begitu rela. Aku bukan seorang tawanan lagi.
Kamera itu belum berhenti merekam, beberapa saat yang terdengar hanya desiran angin yang menyentuh tirai dari jendela yang masih terbuka. Kemudian dering telepon berbunyi, setelah answering machine menjawab, menggema jernih suara seorang laki-laki:
Angkat teleponmu, Elsya sayang. Aku tahu kau ada di kamarmu. Angkat sayang maafkan aku untuk menghilang selama ini setelah pertengkaran besar dengan istriku . Hubungan kita ketahuan sayangku dan ia minta bercerai, rupanya Tuhan mengabulkan doamu (laki-laki itu tertawa).
Elsya, sayangku, manisku..kau dengar aku kan? Plis angkat teleponmu , bidadariku. Kita bisa merencanakan pernikahan kita, aku akan datang esok hari dan kan kita habiskan sepanjang waktu untuk bercinta. Elsya…Elsya..Elsya…..
Suara itu makin melemah, seirama denyut nadi perempuan yang terbaring di atas ranjang berlapis sutra. Lalu suara itu menghilang seiring buih putih yang mengalir di sudut bibirnya. Elsya benar-benar tidur kini, sempurna lepas dari seluruh yang menawan dirinya.*
Susy Ayu, Februari 2011
(Sketsa Ipe Maaruf dimuat dalam buku kumcer "Perempuan Di Balik Kabut")
Kini ia menatap cermin, keningnya basah oleh peluh, disapunya perlahan menyusuri leher lalu berhenti di dadanya yang masih saja bergantung indah, entah sudah berapa laki-laki yang pernah meningalkan jejak samar di sana selain seorang anaknya. Ada guratan sangat halus nyaris tak terlihat di ujung kedua matanya, namun masih saja tampak indah untuk gambaran seorang perempuan berusia di atas tiga puluh tahun. Cerlang matanya meredup, ada warna gelap di kantung matanya, wajahnya kusut, ah…ia terlalu banyak minum semalam. Namun hanya dari situ ia mendapatkan gelora, gairah untuk terus bertahan dan menikmati keutuhan cintanya pada laki-laki itu yang sering datang sebagai bayang-bayang dari pada kenyataan.
Tubuh putihnya yang setengah telanjang menggeser perlahan, meraih setumpuk surat yang belum lagi dibaca. Ia sudah tahu apa isinya tanpa perlu membukanya. Kabar tentang ayah ibunya yang sudah renta di kampung, bibinya, kakaknya, seorang anaknya, kemudian sederetan angka-angka yang mesti ia kirimkan untuk menghidupi semua orang tercinta itu. Perasaan nelangsa , kesepian dan kemarahan yang terpendam begitu rupa membuat ia tidak bersemangat untuk memikirkan siapapun. Mengapa ia biarkan dirinya terlanda damba cinta dan hangat seperti ini? Seharusnya tak perlu, hanya bikin siksa.
Sebelah kakinya bersila di atas kursi, g-stringnya merebak, sekali saja seakan tanpa sengaja ia usap belahan di antara dua pangkal pahanya, basah. Andai saja ia masih berhak menerima setiap pria yang menginginkannya, tentu tak perlu merasa kesepian. Banyak hal yang bisa membuatnya lupa akan pedihnya, paling tidak ia tidak akan pernah merasakan sungguh-sungguh sendirian. Walau mungkin semu.
Genap delapan minggu tanpa laki-laki itu, tanpa pertarungan bersimbah keringat, tanpa pergumulan yang disudahi dengan jeritan panjangnya. Bangsat betul! Laki-laki itu menyimpannya untuk dinikmati sendiri, juga disimpan untuk diasingkan, tak terjamah, tak tersentuh. Delapan kali minggu laki-laki itu mengingkari janjinya, tiada kabar, tiada pesan yang tertinggal. Semua sms yang ia kirimkan ber- report: pending. Hanya suara perempuan yang diatur secara otomatis menyambut suaranya. Halo…halo…. Aku lelah! Aku lelah hidup seperti ini. Nikahi aku saja atau lepaskan aku kembali ke tengah malam.
Untuk kesekian kali ia pandangi wajahnya di cermin, meraih sebatang rokok, membakarnya. Seperti iseng, ia mencore-coret wajahnya dengan kosmetik, berusaha terus menerus mengganti identitasnya. Ia melakukannya sambil terus merokok, tiap satu coretan ia berhenti, mengamati lekat-lekat wajah yang terpantul dari cermin. Siapa ini? Akukah? Seperti apa aku ini? Namun tiap kali ia berhenti dan memandang dirinya sendiri yang tertangkap hanya kepulan tipis asap rokok seperti tirai di hadapan wajahnya. Menangakap bayangan wajahnya sendiripun tak lagi bisa, dan ia tak perduli. Enyahlah kau perempuan malang di dalam cermin! Makin ia tebalkan asap itu, terus menerus hingga kamarnya putih kelabu, sampai ia terhenti sebab kepulan asap itu seperti jemari yang menyekik lehernya.
Ia menyeret langkahnya tanpa semangat, membungkuk meraih tas di kolong ranjang dan mengeluarkan sebuah handycam dari dalam tasnya. Kemudian ia memutarnya, di displaynya terlihat wajahnya sendiri, pada waktu yang lain.
DI LCD
(Ia duduk di atas ranjang, bersila, penuh telanjang, menjepit sebatang rokok yang belum dinyalakn di antara jemarinya)
Semua ini tentang kesedihanku, terperangkap di istana ini, berdandan, mematut-matut diri di cermin dengan lingerie yang selalu baru untuk menyita perhatianmu, berusaha kerasa melahap pengetauan bersetubuh dengan gaya baru untukmu. Namun, kita bukan suami-istri, aku hanya simpananmu….
(Tampak ia mengusap ujung dadanya dengan punggung tangannya)
Aku benci kenapa aku harus mengingat-ingat, kenapa aku tak boleh lupa bahwa aku hanya simpananmu. Dilarang keras bergandengan mesra denganmu di keramaian, tidak kau bawa di undangan teman-temanmu, kau hanya menyimpanku baik-baik di sini, tak boleh terjamah selain kau, mesti selalu segar dan merangsangmu. Setiap kali kau mau. Aku hanya ingin kau ada kali ini, lalu kita bercakap, agar kau tau ini real, rasa sakitku nyata.
( Ia tertunduk, mengusap pelan sudut matanya yang mulai basah)
Terdengar suara berdecit,ia menekan tombol fastforward tanpa melepaskan tombol play-nya. Lalu berhenti di sebuah gambar:
Di LCD
(Ia menyelipkan paha laki-laki berumur lima puluh lima tahun itu di pangkal antara dua kakinya yang mulus, keduanya penuh telanjang)
Aku kesepian, aku telah kehilangan banyak hal. Kau tidak pernah mengenal rasa kehilangan.
(Tangan laki-laki itu meremas dadanya, seakan gemas, tak habis-habis, kemudian tangan itu tinggal di putingnya)
Kau punya segalanya kini, manisku.
(Ia merapatkan tubuhnya , lebih dekat ke dada laki-laki itu)
Tapi aku tidak memilikimu.
(laki-laki itu sedikit gusar, ia meraih selimut, pejamkan mata, tak bersemangat)
Bukankah ku penuhi segala kebutuhanmu?
(Merajuk, ia lebih merapat lagi)
Kau berjanji menikahiku, kita adalah sepasang kekasih kan? Atau aku hanya simpananmu saja?
(Laki-laki itu lebih gusar lagi, menggeser tubuhnya agar menjauh)
Menikah? Kau setuju begini sajakan pada awalnya? Kenapa tiba-tiba minta dinikahi? Cobalah realistis, Elsya. Yang penting tidak ada wanita lain. Selain kau, hanya istriku. Aku tidak bisa menceraikannya, Elsya, itu tidak masuk akal. Ah, matikan kamera itu, aku tidak suka kau merekam!
(Segera ia membelakangi laki-laki itu, hatinya patah, bukan untuk merajuk)
Lebih baik aku kembali menyanyi di club, tak seorangpun memiliki aku , juga tak seorangpun yang kumiliki. Itu lebih adil.
(Laki-laki itu terkejut, tak menduga, cepat saja laki-laki itu meraih tubuhnya, menyibak selimut, meloncat ke atasnya kemudian menindihnya)
Tenang, manis. Jangan kembali ke club, baiklah, aku akan pikirkan hal ini. Kita akan menikah……maka jadilah pengantinku malam ini……
(kemudian dua tubuh itu saling bertindihan dan terguncang di balik selimut yang dibalutkan dan terdengar suara ranjang mewah yang seharusnya tidak berderit)
Ia menekan tombol stop dengan mata yang merah dan basah. Gambar itu sembilan minggu yang lalu, ia ambil sebelum laki-laki itu tak berkabar.
Kemudian ia bangkit lalu membuka jendela apartemennya, langit meredup dengan cakrawala bernuansa sephia, menantang gedung-gedung tinggi yang menyinarkan lampunya. Ah, seakan ia berdiri di tengah panggung, suara beat yang berdetak meruntuhkan jantung, suara-suara sintetik. Cahaya berwarna merkuri menerpa sebagian wajahnya. Cantik wajah itu cemerlang, namun matanya hampa. Tubuhnya seperti bidadari yang terluka, perlahan berubah menjadi seekor serangga yang siap membenturkan dirinya pada nyala yang panas.
Nyanyian itu memerangkapnya begitu rupa, ia mulai mengulang-ngulang sebuah bait, seperti meracau, seperti menjerit, seperti berteriak, tercekat berulang kali kemudian ia sungguh tercekik. Lalu ia jatuh di pinggiran ranjang dengan sengal napas dalam telungkup tubuhnya. Ia tampak begitu kesakitan.
Namun ia segera bangkit melupakan rasa sakitnya, melakukan ritual di depan cermin, sangat berhati-hati bagaikan sebuah upacara. Membubuhkan bedak penuh khidmat, sekali lagi ia terpenjara dalam perasaannya sendiri. Sambil bersenandung ia mengusap pelan wajahnya, lehernya dadanya, putting susunya. Ia berdiri, menari-nari, berputar, meliuk dengan sangat erotis. Ketika selesai lagunya dinyanyikan, ia kelelahan, terengah-engah seperti terpuaskan berkali-kali. Kembali ia menatap wajahnya di cermin yang selalu saja menjadi semakin asing, siapakah perempuan di cermin ini? Tak usah perduli, kepulkan saja asap rokokmu, tebalkan, agar kau tak lihat siapa ia.
Kau hanya perlu tidur panjang, Elsya. Perempuan malang, tidurlah agar berhenti juga kau rasakan deritamu. Dalam lelapmu nanti, kau akan terbebas dari segala nelangsa.
Ia meraih gaun putih berdada rendah, mengenakannya. Seketika tampil seorang perempuan matang yang begitu menawan, begitu berkelas, begitu anggun. Tapi perempuan ini nyata-nyata begitu rapuh, seperti gerabah. Sebenarnya ia tak ingin banyak hal, hanya ingin meraih cinta yang belum pernah ada dalam hidupnya. Tetapi yang tinggal adalah segerombolan serigala liar yang berkeliling di sekitarnya, siap menerkam dan menikmati cabikan tubuhnya. Serigala yang paling kejam adalah James, wajah pria itu muncul dengan tubuh binatang. James, pemilik club. Ia menyanyi di club sekaligus menjadi pemuas hasrat James, menyusul jadi santapan bagi serigala lain yang kelaparan, sahabat-sahabat dan tamu-tamu si pemilik club.
Lalu seseorang datang laksana penyelamat, menebusnya dari club setahun ini, menafkahi keluarganya, mengikatnya. Dan cinta datang kemudian, pada laki-laki yang telah beristri dan tidak mungkin dapat menikahinya atas dasar sebuah nama baik. Namun bila laki-laki itu beranjak darinya, maka sebagian dirinya akan mati.
Ia meletakkan kamera pada tripodnya, duduk bersila di atas ranjang berhadapan dengan kameranya. Gaun putih menutup lembut seluruh tubuh mulusnya, hanya pucuk dadanya yang mengeras mengintip dari sebalik gaunnya. Wajahnya pucat, namun sangat pasrah, berjuta gurat lelah akan pedih masih jelas terlukis, takkan terhapus.
Di viewfinder kamera itu, terlihat ia menggenggam remote. Lalu ia mulai merekam:
“Ini adalah kesedihanku yang kesekian, ketika tak juga aku dapat bangkit dan membuat hatiku menjadi lebih kuat. Aku terlalu letih untuk mengarungi hidup ini selanjutnya. Kepada yang mencintaiku, maafkan aku karena rapuhku, karena dendamku pada masa lalu yang melukaiku, juga karena cintaku pada seorang laki-laki yang tak dapat kutanggungkan sendirian. Hatiku tak cukup luas untuk menampung cinta ini, aku tak bisa hidup dengan laki-laki tanpa cinta pun tak bisa hidup tanpanya. Selalu saja cintaku tumbuh di tempat yang salah. Sungguh aku patah lagi. Maafkan atas salahku ini, yang kusadari namun sangat terlambat.”
Kamera itu masih menangkap gambar saat ia menenggak air putih benyak-banyak tiap kali setelah menjejalkan sejumlah dari puluhan butir obat tidur ke mulutnya, sampai botol itu kosong. Lalu mengucapkan sesuatu sebelum merebahkan dirinya dengan lembut di atas ranjang dan memejamkan matanya. Begitu rela. Aku bukan seorang tawanan lagi.
Kamera itu belum berhenti merekam, beberapa saat yang terdengar hanya desiran angin yang menyentuh tirai dari jendela yang masih terbuka. Kemudian dering telepon berbunyi, setelah answering machine menjawab, menggema jernih suara seorang laki-laki:
Angkat teleponmu, Elsya sayang. Aku tahu kau ada di kamarmu. Angkat sayang maafkan aku untuk menghilang selama ini setelah pertengkaran besar dengan istriku . Hubungan kita ketahuan sayangku dan ia minta bercerai, rupanya Tuhan mengabulkan doamu (laki-laki itu tertawa).
Elsya, sayangku, manisku..kau dengar aku kan? Plis angkat teleponmu , bidadariku. Kita bisa merencanakan pernikahan kita, aku akan datang esok hari dan kan kita habiskan sepanjang waktu untuk bercinta. Elsya…Elsya..Elsya…..
Suara itu makin melemah, seirama denyut nadi perempuan yang terbaring di atas ranjang berlapis sutra. Lalu suara itu menghilang seiring buih putih yang mengalir di sudut bibirnya. Elsya benar-benar tidur kini, sempurna lepas dari seluruh yang menawan dirinya.*
Susy Ayu, Februari 2011
(Sketsa Ipe Maaruf dimuat dalam buku kumcer "Perempuan Di Balik Kabut")
Catatan Seno Gumira Pada Buku Cerpen "Perempuan Di Balik Kabut"
Demikianlah disebutkan, bahwa pertanyaan esensial bukan lagi penulis dan tulisan, melainkan menulis dan membaca. Dalam konsep ini, perhatian kepada penulis dijauhkan sebagai sumber makna, seperti juga tulisan sebagai objek, dan sebagai gantinya perhatian dipusatkan kepada dua jaringan kebiasaan yang berkorelasi: menulis sebagai suatu institusi dan membaca sebagai suatu kegiatan.
Dengan pengantar sependek ini, izinkanlah saya langsung mengeluarkan Susy Ayu sebagai subjek individual dalam perbincangan, karena ketika bahkan tulisan ditolak menjadi objek, yang tersisa hanyalah subjek sosial yang berbicara dalam tulisan, yang hanya akan muncul dalam pembacaan saya ketika kembali, lagi-lagi sebagai tulisan—yang sekali lagi hanya akan ter/di-hidupkan dalam pembacaan. Itulah, pembacaan dan penulisan adalah suatu proses yang maknanya terus menerus berubah, sementara penulis hanyalah medium—ibarat dukun kemasukan roh yang akan berbicara bukan atas nama dirinya pribadi—dan tulisan hanyalah jejak, satu-satunya jejak dan bukan kenyataan itu sendiri.
Jejak sebagai artefak kebudayaan? Tentu. Namun kebudayaan macam apa? Di sanalah akan terjejaki pergulatan antarwacana. Sejauh bisa saya klebet kumpulan cerpen Perempuan di Balik Kabut ini, dan bukannya sisir seperti—yang seharusnya—menyisir kutu, maka pergulatan yang untuk sementara ini menonjol untuk dijejaki adalah pergulatan antara wacana cinta dan wacana birahi.
Baiklah saya ungkapkan saja sejumlah sample hasil peng-klebet-an itu:
… lingerie yang selalu baru untuk menyita perhatianmu, berusaha keras melahap pengetahuan bersetubuh dengan gaya baru untukmu. Namun, kita bukan suami istri, aku hanya simpananmu….(“Langit Sephia Berbingkai Jendela”)
Namun tahukah kau, Zal. Aku pun bisa hamil. Aku pernah hamil! Laki-laki teman seragam abu-abuku dulu yang melakukannya, di saat kami berdua melayang di tengah asap putaw. / Aku juga perempuan sejati, bisa hamil seperti Dewimu. Aku pun memiliki cinta yang tulus, seperti Dewimu. (“Tiket Sekali Jalan”)
Bercinta di tepi pantai adalah impianku, Mas. Penyatuan jiwa dan cinta dengan suasana yang begitu hangat. Hal itu terasa indah bila dilakukan dengan orang yang paling tercinta. Berpelukan mesra, saling berbisik, bercumbu dengan sayang… lalu kita bercinta dengan penuh gelora…..(“Antara Jalan Tol dan Tepi Pantai”)
“Ssst. Sabtu dan Minggu depan. Aku sudah pamit kepada istriku, aku hendak dinas ke luar kota. Bisakah kau?” Aku bergairah membaca pesannya./ Kali ini jariku mengetik pesan untuk orang lain, “Ma, aku baru dapat tugas untuk ke luar kota pada Sabtu dan Minggu depan.” Pesanku itu sampai ke ponsel istriku. (“Borges dan Labirinku”)
Dia menyerah, tetapi tidak sinar matanya. Tubuhnya terbuka tanpa perlawanan, kelopaknya tersibak, setengah megap-megap dia menyusun kata-kata.
“Silakan kalau kau mau. Setelah ini jangan pernah berharap untuk ketemu aku lagi. Aku akan berdoa, kamulah laki-laki terakhir yang paling kubenci.”/ “Tidak dengan ini karena aku mulai mencintaimu,” suaranya parau, kupikir matanya basah. (“Perempuan di Balik Kabut”)
Kutunjukkan pada laki-laki… aku masih saja bisa nikmat meski tidak lagi perawan! (“Rahasia Hati”)
….., di usiaku yang ke-36, susuku masih sekencang delima, hanya saja dengan suami megap-megap macam ini aku merasa agak tersinggung. Tapi ia sekarat, aku bisa melihatnya. / Perasaanku berdebar. Di balik pintu, kekasihku menunggu dengan simpati yang sempurna. Selama suamiku menarik napasnya satu-satu dalam 18 jam ini, ia telah menyentuhkan telapak tangannya yang terasa hangat empat kali ke pinggulku, meremasnya / Ia tahu itu menciptakan perasaan riang yang bergelora dalam diriku. Usianya 27 tahun. Mengingat staminanya yang kuukur secara rahasia lewat penyelinapan-penyelinapan kami, aku bisa merasakan, waktu sekaratnya masih lama lagi. (“Nota Perkawinan”)
Dalam birahi, kehidupan dan kematian bersatu. Dalam birahi, kau dan aku cabar seperti kabut. Dalam birahi, aku lenyap dalam dirimu. Maka perempuan, susui aku lagi. Biar kusesap habis dirimu, sebab dinamakannya kau Hawa, lantaran kau adalah ibu dari segala kehidupan. (“Kunamai Kau Kenangan”)
Dari 12 cerita pendek, jika setidaknya delapan di antaranya mengungkap artefak semacam ini, kiranya sahih untuk berbincang, antara wacana birahi dan wacana cinta, bagaimana keduanya telah bergulat?
Sebelum itu, tentu mesti saya rentangkan lebih dahulu konstruksi oposisional keduanya dalam wacana dominan, yakni bahwa birahi selalu disamakan dengan nafsu seksual, dan dengan itu akan selalu mengotor-ngotori kesucian cinta—sedangkan cinta itu sendiri hanya sahih dalam mahligai perkawinan. Di luar lembaga pengesahan hubungan seksual tersebut, dengan atau tanpa cinta, hubungan tersebut bermasalah, bahkan resminya ‘taksuci’ lagi.
Maka, kerangka konstruksi wacana dominan tersebut tentu seperti berikut:
Cinta = Suci = Perkawinan >< Birahi = Taksuci = Luar-Perkawinan
Sekarang, jika kita ikuti hasil pengujian dengan ‘teori’ semacam itu, hasilnya adalah seperti berikut:
1. “Langit Sephia Berbingkai Jendela” – Birahi/Taksuci/Luar-Perkawinan = Cocok
2. “Tiket Sekali Jalan” – Birahi/Taksuci/Luar-Perkawinan = Cocok
3. “Antara Jalan Tol dan Tepi Pantai – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
4. “Borges dan Labirinku” – Cinta/Birahi/Luar-Perkawinan = Takcocok
5. “Perempuan di Balik Kabut” – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
6. “Rahasia Hati” – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
7. “Nota Perkawinan” – Cinta/Birahi/Luar-Perkawinan = Takcocok
8. “Kunamai Kau Kenangan” – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
Pembaca tentu harus mencocokkan lagi simpulan serba sementara ini dengan cerita pendeknya secara utuh, karena yang saya ambil adalah moralitasnya—sehingga bisa saja pasangan dalam cerita tersebut memang belum menikah, seperti dalam “Perempuan di Balik Kabut”, tetapi ketika tokoh perempuannya menolak penerusan hubungan seksual, meski sudah tenggelam dalam birahi, justru karena cinta, itu berarti ia menghendaki perkawinan bagi pengesahan cinta plus birahinya tersebut.
Dalam “Borges dan Labirinku” para pelaku yang berselingkuh, dengan cinta, sama-sama beristri (= keduanya pria)—ini tidak mengubah konstruksi oposisional dalam wacana dominan yang diujikan kepadanya, yang ternyata memang takcocok.
Sementara dalam “Rahasia Hati”, suatu pernikahan batal karena faktor takperawan, tetapi pendapat bahwa faktor itu takberpengaruh pada kenikmatan seksual, jelas membenarkan kesahihan birahi dalam cinta dan perkawinan, alias takcocok dengan konstruksi oposisional wacana dominan, yang dalam peng-klebet-an-rada-serabutan ini tampaknya sudah takdominan lagi—karena hanya dua cerita yang memenuhi kecocokannya.
Dalam konstruksi wacana yang sudah takcocok pada enam cerita, meski sama-sama takcocok, terdapat berbagai varian, misalnya bahwa ternyata ketakcocokan meleburnya cinta (=suci) dan birahi (=taksuci) bisa terdapat di luar maupun di dalam lembaga perkawinan itu sendiri.
Sedangkan yang menyamakan keenam-enamnya, justru peleburan cinta dan birahi tersebut. Bolehkah yang suci itu sekaligus bernafsu birahi? Dalam konteks hubungan seksual, tampaknya justru konstruksi wacana inilah yang sekarang dominan, menggantikan konstruksi oposisional sebelumnya, bahwa cinta yang suci terpisahkan dari birahi yang taksuci.
Disimpulkan kembali, bukan lembaga perkawinan yang menjadi faktor pengesahan hubungan seksual—kali ini selalu dengan birahi—melainkan cinta. Apakah harus kita sebut lembaga cinta? Barangkali tidak, sebab ketika cinta dilembagakan, ia akan berhenti sebagai cinta… Seperti banyak perkawinan yang berhasil melembagakan hubungan seksual, tetapi gagal menghidupkan cinta itu sendiri, yang pada gilirannya mematikan segala-galanya.
Yang suci memang cinta, di dalam maupun di luar lembaga perkawinan, seperti yang secara dominan merupakan wacana dalam kumpulan cerita Perempuan di Balik Kabut ini—sampai artefak kebudayaan lain menggugurkannya.
Seperti juga mitos, bahwa hanya perempuan yang bisa hamil layak disebut perempuan sejati dalam cerita “Tiket Sekali Jalan”, yang telah gugur, tidak ada yang abadi di dunia ini—sehingga jika cinta tetap ingin bertahan, memang harus selalu diperjuangkan kembali, lagi, lagi, dan lagi…
Salam.
Seno Gumira Ajidarma
Kampung Utan, Selasa 18 Oktober 2011
Dengan pengantar sependek ini, izinkanlah saya langsung mengeluarkan Susy Ayu sebagai subjek individual dalam perbincangan, karena ketika bahkan tulisan ditolak menjadi objek, yang tersisa hanyalah subjek sosial yang berbicara dalam tulisan, yang hanya akan muncul dalam pembacaan saya ketika kembali, lagi-lagi sebagai tulisan—yang sekali lagi hanya akan ter/di-hidupkan dalam pembacaan. Itulah, pembacaan dan penulisan adalah suatu proses yang maknanya terus menerus berubah, sementara penulis hanyalah medium—ibarat dukun kemasukan roh yang akan berbicara bukan atas nama dirinya pribadi—dan tulisan hanyalah jejak, satu-satunya jejak dan bukan kenyataan itu sendiri.
Jejak sebagai artefak kebudayaan? Tentu. Namun kebudayaan macam apa? Di sanalah akan terjejaki pergulatan antarwacana. Sejauh bisa saya klebet kumpulan cerpen Perempuan di Balik Kabut ini, dan bukannya sisir seperti—yang seharusnya—menyisir kutu, maka pergulatan yang untuk sementara ini menonjol untuk dijejaki adalah pergulatan antara wacana cinta dan wacana birahi.
Baiklah saya ungkapkan saja sejumlah sample hasil peng-klebet-an itu:
… lingerie yang selalu baru untuk menyita perhatianmu, berusaha keras melahap pengetahuan bersetubuh dengan gaya baru untukmu. Namun, kita bukan suami istri, aku hanya simpananmu….(“Langit Sephia Berbingkai Jendela”)
Namun tahukah kau, Zal. Aku pun bisa hamil. Aku pernah hamil! Laki-laki teman seragam abu-abuku dulu yang melakukannya, di saat kami berdua melayang di tengah asap putaw. / Aku juga perempuan sejati, bisa hamil seperti Dewimu. Aku pun memiliki cinta yang tulus, seperti Dewimu. (“Tiket Sekali Jalan”)
Bercinta di tepi pantai adalah impianku, Mas. Penyatuan jiwa dan cinta dengan suasana yang begitu hangat. Hal itu terasa indah bila dilakukan dengan orang yang paling tercinta. Berpelukan mesra, saling berbisik, bercumbu dengan sayang… lalu kita bercinta dengan penuh gelora…..(“Antara Jalan Tol dan Tepi Pantai”)
“Ssst. Sabtu dan Minggu depan. Aku sudah pamit kepada istriku, aku hendak dinas ke luar kota. Bisakah kau?” Aku bergairah membaca pesannya./ Kali ini jariku mengetik pesan untuk orang lain, “Ma, aku baru dapat tugas untuk ke luar kota pada Sabtu dan Minggu depan.” Pesanku itu sampai ke ponsel istriku. (“Borges dan Labirinku”)
Dia menyerah, tetapi tidak sinar matanya. Tubuhnya terbuka tanpa perlawanan, kelopaknya tersibak, setengah megap-megap dia menyusun kata-kata.
“Silakan kalau kau mau. Setelah ini jangan pernah berharap untuk ketemu aku lagi. Aku akan berdoa, kamulah laki-laki terakhir yang paling kubenci.”/ “Tidak dengan ini karena aku mulai mencintaimu,” suaranya parau, kupikir matanya basah. (“Perempuan di Balik Kabut”)
Kutunjukkan pada laki-laki… aku masih saja bisa nikmat meski tidak lagi perawan! (“Rahasia Hati”)
….., di usiaku yang ke-36, susuku masih sekencang delima, hanya saja dengan suami megap-megap macam ini aku merasa agak tersinggung. Tapi ia sekarat, aku bisa melihatnya. / Perasaanku berdebar. Di balik pintu, kekasihku menunggu dengan simpati yang sempurna. Selama suamiku menarik napasnya satu-satu dalam 18 jam ini, ia telah menyentuhkan telapak tangannya yang terasa hangat empat kali ke pinggulku, meremasnya / Ia tahu itu menciptakan perasaan riang yang bergelora dalam diriku. Usianya 27 tahun. Mengingat staminanya yang kuukur secara rahasia lewat penyelinapan-penyelinapan kami, aku bisa merasakan, waktu sekaratnya masih lama lagi. (“Nota Perkawinan”)
Dalam birahi, kehidupan dan kematian bersatu. Dalam birahi, kau dan aku cabar seperti kabut. Dalam birahi, aku lenyap dalam dirimu. Maka perempuan, susui aku lagi. Biar kusesap habis dirimu, sebab dinamakannya kau Hawa, lantaran kau adalah ibu dari segala kehidupan. (“Kunamai Kau Kenangan”)
Dari 12 cerita pendek, jika setidaknya delapan di antaranya mengungkap artefak semacam ini, kiranya sahih untuk berbincang, antara wacana birahi dan wacana cinta, bagaimana keduanya telah bergulat?
Sebelum itu, tentu mesti saya rentangkan lebih dahulu konstruksi oposisional keduanya dalam wacana dominan, yakni bahwa birahi selalu disamakan dengan nafsu seksual, dan dengan itu akan selalu mengotor-ngotori kesucian cinta—sedangkan cinta itu sendiri hanya sahih dalam mahligai perkawinan. Di luar lembaga pengesahan hubungan seksual tersebut, dengan atau tanpa cinta, hubungan tersebut bermasalah, bahkan resminya ‘taksuci’ lagi.
Maka, kerangka konstruksi wacana dominan tersebut tentu seperti berikut:
Cinta = Suci = Perkawinan >< Birahi = Taksuci = Luar-Perkawinan
Sekarang, jika kita ikuti hasil pengujian dengan ‘teori’ semacam itu, hasilnya adalah seperti berikut:
1. “Langit Sephia Berbingkai Jendela” – Birahi/Taksuci/Luar-Perkawinan = Cocok
2. “Tiket Sekali Jalan” – Birahi/Taksuci/Luar-Perkawinan = Cocok
3. “Antara Jalan Tol dan Tepi Pantai – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
4. “Borges dan Labirinku” – Cinta/Birahi/Luar-Perkawinan = Takcocok
5. “Perempuan di Balik Kabut” – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
6. “Rahasia Hati” – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
7. “Nota Perkawinan” – Cinta/Birahi/Luar-Perkawinan = Takcocok
8. “Kunamai Kau Kenangan” – Cinta/Birahi/Perkawinan = Takcocok
Pembaca tentu harus mencocokkan lagi simpulan serba sementara ini dengan cerita pendeknya secara utuh, karena yang saya ambil adalah moralitasnya—sehingga bisa saja pasangan dalam cerita tersebut memang belum menikah, seperti dalam “Perempuan di Balik Kabut”, tetapi ketika tokoh perempuannya menolak penerusan hubungan seksual, meski sudah tenggelam dalam birahi, justru karena cinta, itu berarti ia menghendaki perkawinan bagi pengesahan cinta plus birahinya tersebut.
Dalam “Borges dan Labirinku” para pelaku yang berselingkuh, dengan cinta, sama-sama beristri (= keduanya pria)—ini tidak mengubah konstruksi oposisional dalam wacana dominan yang diujikan kepadanya, yang ternyata memang takcocok.
Sementara dalam “Rahasia Hati”, suatu pernikahan batal karena faktor takperawan, tetapi pendapat bahwa faktor itu takberpengaruh pada kenikmatan seksual, jelas membenarkan kesahihan birahi dalam cinta dan perkawinan, alias takcocok dengan konstruksi oposisional wacana dominan, yang dalam peng-klebet-an-rada-serabutan ini tampaknya sudah takdominan lagi—karena hanya dua cerita yang memenuhi kecocokannya.
Dalam konstruksi wacana yang sudah takcocok pada enam cerita, meski sama-sama takcocok, terdapat berbagai varian, misalnya bahwa ternyata ketakcocokan meleburnya cinta (=suci) dan birahi (=taksuci) bisa terdapat di luar maupun di dalam lembaga perkawinan itu sendiri.
Sedangkan yang menyamakan keenam-enamnya, justru peleburan cinta dan birahi tersebut. Bolehkah yang suci itu sekaligus bernafsu birahi? Dalam konteks hubungan seksual, tampaknya justru konstruksi wacana inilah yang sekarang dominan, menggantikan konstruksi oposisional sebelumnya, bahwa cinta yang suci terpisahkan dari birahi yang taksuci.
Disimpulkan kembali, bukan lembaga perkawinan yang menjadi faktor pengesahan hubungan seksual—kali ini selalu dengan birahi—melainkan cinta. Apakah harus kita sebut lembaga cinta? Barangkali tidak, sebab ketika cinta dilembagakan, ia akan berhenti sebagai cinta… Seperti banyak perkawinan yang berhasil melembagakan hubungan seksual, tetapi gagal menghidupkan cinta itu sendiri, yang pada gilirannya mematikan segala-galanya.
Yang suci memang cinta, di dalam maupun di luar lembaga perkawinan, seperti yang secara dominan merupakan wacana dalam kumpulan cerita Perempuan di Balik Kabut ini—sampai artefak kebudayaan lain menggugurkannya.
Seperti juga mitos, bahwa hanya perempuan yang bisa hamil layak disebut perempuan sejati dalam cerita “Tiket Sekali Jalan”, yang telah gugur, tidak ada yang abadi di dunia ini—sehingga jika cinta tetap ingin bertahan, memang harus selalu diperjuangkan kembali, lagi, lagi, dan lagi…
Salam.
Seno Gumira Ajidarma
Kampung Utan, Selasa 18 Oktober 2011
Peluncuran Buku Puisi Susy Ayu: Kata-kata yang Menciptakan Dunia Sendiri
JAKARTA, KOMPAS.com--Kekuatan Susy Ayu terletak pada daya serapnya terhadap ilmu pengetahuan dan penghayatannya pada kehidupan. Demikian pendapat sastrawan Eka Budianta tentang buku kumpulan puisi tunggal Susy Ayu yang berjudul “Rahim Kata-Kata” yang diluncurkan di PDS HB Jassin, Sabtu 19 Juni lalu.
Dalam makalah setebal 10 halaman, yang berjudul “Puisi Sosiokultural Susy Ayu”, Eka menunjuk puisi-puisi Susy yang mengajak pembaca berkenalan dengan Putri Pembayun, Dewi Drupadi, Maria Magdalena, Hercules, Old Shuterhand, dan seterusnya. “Susy Ayu sangat ahli membuka dialog melalui celah-celah referensi seperti itu,” ujarnya. Sementara dalam puisi Rengganis yang tak dimuat dalam buku ini Eka tak kurang-kurang memuji, alangkah kaya dan luasnya pemandangan yang dapat diungkap hanya melalui sebaris atau dua baris puisi Susy Ayu. “Dengan puisi ia telah membuktikan bahwa kata-kata dapat menciptakan jagad tersendiri untuk berbagi,” tambahnya. Susy dengan bakat dan intelektualitasnya telah membagikan berbagai aspirasi melalui puisinya.
Susy Ayu adalah salah seorang penyair yang sebelumnya banyak menulis melalui Fecabook. Sebelumnya, karya-karyanya dimuat dalam antologi puisi 10 penyair Facebook “Merah Yang Merah”, dan “Perempuan dalam Sajak”. Buku “Rahim Kata-Kata” adalah buku kumpulan puisi tunggalnya yang pertama. Buku setebal 52 halaan itu, dieditori oleh Kurniawan Junaedhie, dan diberi endorsement oleh Maman S Mahayana, Acep Zamzam Noor dan Kurnia Effendi.
Acara peluncuran dan diskusi buku kumpulan puisi itu sendiri, dihadiri para penyair dan seniman dari berbagai angkatan seperti Adri Darmadji Woko, Dharmadi, Remmy Novaris DM, Kurnia Effendi, Ana Mustamin dll. Acara itu digelar di PDS HB Jassin, TIM, Sabru 19 Juni 2010. Tampil membacakan puisi antara lain penyair Kurniawan Junaedhie, Shinta Miranda, Nona Muchtar dan lain-lain.
Saat ini penyair perempuan sangat sedikit, sehingga pesaing Susy untuk menjadi penyair perempuan andal terbuka lebar, demikian Eka.***(Ist)
Jodhi Yudono | Senin, 21 Juni 2010
http://oase.kompas.com/read/2010/06/21/02041265/Kata.kata.yang.Menciptakan.Dunia.Sendiri
-------------------------------
#RAHIM KATA-KATA, kump. puisi Susy Ayu. Sebuah bentuk rasa syukur atas jejak usia 38 thn, tgl 14 Juni 2010.58 hal + viii. ISBN: 978-602-96333-7-5. Editor: Kurniawan Junaedhie. Endorser: Maman S Mahayana, Acep Zamzam Noer & Kurnia Effendi.#
Membaca puisi-puisi Susy Ayu, saya seperti berhadapan dengan “aku lirik” yang dibetot dua kekuatan: bukan sebagai paradoks, bukan juga sebagai kontradiksi. Di satu sisi, ada hasrat untuk mengungkapkan banyak hal: tentang sejarah masa lalu, mitologi atau jiwa yang menyatu dan terbelah. Di sisi yang lain, ada sebagian yang ingin tetap disembunyikan; rahasia yang sengaja dinikmati. Tema-tema ambivalensi seperti hendak menyergap kita. Maka, di sana-sini–dalam antologi ini–ada main-main yang serius; ada kenakalan dalam kesantunan; ada perlawanan yang tersimpan dalam kesetiaan. Nah!
(Maman S Mahayana, Pengajar Tamu Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea)
Dalam berpuisi Susy Ayu nampaknya bukan sekedar merangkai kata, namun ada kesadaran untuk selalu memberinya muatan makna. Maka lewat puisi-puisi yang ditulisnya kita akan menemukan banyak pernyataan dan gugatan yang mempersoalkan eksistensi perempuan dalam kaitannya dengan gender. Bahkan pada sejumlah puisi terbaiknya, pernyataan dan gugatan tersebut terasa begitu keras dan lantang. Hanya saja Susy Ayu berhasil membungkusnya dengan bahasa simbolis yang indah dan merdu. Bahasa yang khas puisi.
(Acep Zamzam Noor, Penyair)
Susy Ayu telah sampai pada persimpangan dalam mengolah materi, antara yang terdorong oleh imajinasi impulsif dan yang dituang dari pengendapan pembacaan. Keindahan berikutnya adalah keberaniannya memberi warna sensual, sehingga sejumlah puisinya seperti memiliki kerling yang menggoda.
(Kurnia Effendi, penulis memoar Hee Ah Lee, “The Four Fingered Pianist”)
Dalam makalah setebal 10 halaman, yang berjudul “Puisi Sosiokultural Susy Ayu”, Eka menunjuk puisi-puisi Susy yang mengajak pembaca berkenalan dengan Putri Pembayun, Dewi Drupadi, Maria Magdalena, Hercules, Old Shuterhand, dan seterusnya. “Susy Ayu sangat ahli membuka dialog melalui celah-celah referensi seperti itu,” ujarnya. Sementara dalam puisi Rengganis yang tak dimuat dalam buku ini Eka tak kurang-kurang memuji, alangkah kaya dan luasnya pemandangan yang dapat diungkap hanya melalui sebaris atau dua baris puisi Susy Ayu. “Dengan puisi ia telah membuktikan bahwa kata-kata dapat menciptakan jagad tersendiri untuk berbagi,” tambahnya. Susy dengan bakat dan intelektualitasnya telah membagikan berbagai aspirasi melalui puisinya.
Susy Ayu adalah salah seorang penyair yang sebelumnya banyak menulis melalui Fecabook. Sebelumnya, karya-karyanya dimuat dalam antologi puisi 10 penyair Facebook “Merah Yang Merah”, dan “Perempuan dalam Sajak”. Buku “Rahim Kata-Kata” adalah buku kumpulan puisi tunggalnya yang pertama. Buku setebal 52 halaan itu, dieditori oleh Kurniawan Junaedhie, dan diberi endorsement oleh Maman S Mahayana, Acep Zamzam Noor dan Kurnia Effendi.
Acara peluncuran dan diskusi buku kumpulan puisi itu sendiri, dihadiri para penyair dan seniman dari berbagai angkatan seperti Adri Darmadji Woko, Dharmadi, Remmy Novaris DM, Kurnia Effendi, Ana Mustamin dll. Acara itu digelar di PDS HB Jassin, TIM, Sabru 19 Juni 2010. Tampil membacakan puisi antara lain penyair Kurniawan Junaedhie, Shinta Miranda, Nona Muchtar dan lain-lain.
Saat ini penyair perempuan sangat sedikit, sehingga pesaing Susy untuk menjadi penyair perempuan andal terbuka lebar, demikian Eka.***(Ist)
Jodhi Yudono | Senin, 21 Juni 2010
http://oase.kompas.com/read/2010/06/21/02041265/Kata.kata.yang.Menciptakan.Dunia.Sendiri
-------------------------------
#RAHIM KATA-KATA, kump. puisi Susy Ayu. Sebuah bentuk rasa syukur atas jejak usia 38 thn, tgl 14 Juni 2010.58 hal + viii. ISBN: 978-602-96333-7-5. Editor: Kurniawan Junaedhie. Endorser: Maman S Mahayana, Acep Zamzam Noer & Kurnia Effendi.#
Membaca puisi-puisi Susy Ayu, saya seperti berhadapan dengan “aku lirik” yang dibetot dua kekuatan: bukan sebagai paradoks, bukan juga sebagai kontradiksi. Di satu sisi, ada hasrat untuk mengungkapkan banyak hal: tentang sejarah masa lalu, mitologi atau jiwa yang menyatu dan terbelah. Di sisi yang lain, ada sebagian yang ingin tetap disembunyikan; rahasia yang sengaja dinikmati. Tema-tema ambivalensi seperti hendak menyergap kita. Maka, di sana-sini–dalam antologi ini–ada main-main yang serius; ada kenakalan dalam kesantunan; ada perlawanan yang tersimpan dalam kesetiaan. Nah!
(Maman S Mahayana, Pengajar Tamu Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea)
Dalam berpuisi Susy Ayu nampaknya bukan sekedar merangkai kata, namun ada kesadaran untuk selalu memberinya muatan makna. Maka lewat puisi-puisi yang ditulisnya kita akan menemukan banyak pernyataan dan gugatan yang mempersoalkan eksistensi perempuan dalam kaitannya dengan gender. Bahkan pada sejumlah puisi terbaiknya, pernyataan dan gugatan tersebut terasa begitu keras dan lantang. Hanya saja Susy Ayu berhasil membungkusnya dengan bahasa simbolis yang indah dan merdu. Bahasa yang khas puisi.
(Acep Zamzam Noor, Penyair)
Susy Ayu telah sampai pada persimpangan dalam mengolah materi, antara yang terdorong oleh imajinasi impulsif dan yang dituang dari pengendapan pembacaan. Keindahan berikutnya adalah keberaniannya memberi warna sensual, sehingga sejumlah puisinya seperti memiliki kerling yang menggoda.
(Kurnia Effendi, penulis memoar Hee Ah Lee, “The Four Fingered Pianist”)
“Tarian Ilalang”: Dinamis dan Kokoh
(Ulasan yang disampaikan dalam acara Launching Buku Antologi Puisi Tarian Ilalang
di PDS HB Jassin, Jakarta, Sabtu, 15 Mei 2010)
Tarian Ilalang, sebuah judul buku yang menarik. Kemudian terbayang di benak tentang sekumpulan ilalang , tampak rapuh namun tegak dan oleh angin mereka bergerak sangat dinamis, teratur dan mampu bertahan dalam kekeringan. Ilalang serupa kecemasan sekaligus harapan abadi manusia.
Tarian Ilalang, adalah sebuah buku antologi puisi. Antologi secara harfiah diturunkan dari kata bahasa Yunani yang berarti “karangan bunga” atau “kumpulan bunga”, adalah sebuah kumpulan dari karya-karya sastra. Sementara kata puisi, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani poites, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat.
Kita bisa menyebut beberapa nama: Samuel Taylor Coleridge, Wordsworth, atau Dunton yang memiliki pendapatnya masing masing tentang puisi. Demikian juga kita, setelah menciptakan puisi dengan menjalani proses prosesnya, maka menurut saya puisi adalah merupakan sublimasi gerak perasaan dan pikiran yang terekam dalam kata kata. Sublimasi yang saya maksud tentu saja semacam perenungan/pengendapan yang melahirkan bentuk baru setelah penghayatan.
Dengan kata lain puisi bisa berupa “potret kata kata” atas diri kita atau di luar itu yang berhasil ditangkap dengan mata dan rasa kemudian terolah di dalam bathin, hingga melahirkan pikiran atau gagasan gagasan tentang hal itu di dalam sebuah frame.
Tarian Ilalang, antoloi puisi oleh Adrian Kelana, Arther Panther Olii, Atan Wira Bangsa, Bagus Prana, Faris Al Farisi, Geg Neka, Ira Ginda, Joezefhine Zejoe, Lina Kelana, dan Windy Aurora.
1. Adrian Kelana, dalam pengelanaannya ia menguatkan jejaknya atas asa ( Secawan Anggur Rajahan, hal. 4) dan cinta kepada sesama ( Kemana Asap Tungku Itu, hal. 8 ) juga harapannya (Musafir Kelana, hal 10).
2. Arther Panther Olii, berhasil menggali kepedihannya hingga terasa begitu kental namun mengiris dengan sangat halus pada liris penutupnya : O, tidakkah kalian lihat telah lahir sajak paling pedih dari bening mataku? ( Dan Lahirlah Sajak Paling Pedih Dari Bening Mataku, hal. 18).
3. Safwan Nizar – Athan Wira Bangsa, menghidupkan sajak sajaknya dari perenungan yang digali antara dunia dalam bawah sadar dan dunia dalam kesadaran serta mengantar kita untuk merunduk lebih dalam atas keagungan Illahi ( Aku Mencari-Mu, hal. 26) dan (Tuhan dan Rabi, hal. 27).
4. Bagus Prana, menulis rasa kehilangan dan pencarian akan cinta kasih yang lengkap tak terbelah, menyentuh rasa kemanusiaan kita (Syair Sebuah Balada, Hal. 37) , (Terlepas Sebuah Tanya, hal. 38) dan (Janji Dermaga Biru, hal. 40).
5. Faris Al Farisi, dialog ringan kerap kita temukan pada sajak sajaknya, dan itu membentuk keunikan dalam imaji yang kental (Kremasi, hal. 45) dan (Tentang Batu 4, hal. 50).
6. Geg Neka, sajak sajaknya kerap irit diksi namun lincah dan memiliki makna pada keseluruhan bangunan puisinya. Sajaknya sangat dinamis, enerjik ( Pikiran, hal. 57), (Gelembung, hal. 58) dan tegas dalam lembutnya ( Lembayung, hal. 61).
7. Ira Ginda, nuansa gothic begitu kental membungkus pada kebanyakan puisinya, namun ia mampu membuat imaji imaji dalam gelap itu menjadi nyata di benak kita. Nuansa Romantika Gothic; yang mengungkapkan dunia cinta secara sensual dimana bisa menghasilkan jalinan yang kuat atau kadang tragis menyembul dari imaji imajinya (Kisah Rembulan Buta, hal. 65) dan (Pelacur Di Antara Kedua Kakimu, hal. 71). Dalam nuansa kelam itu Ira juga mampu memberi imaji yang lembut di dalam kehangatan yang miris (Secawan Teh Hangat, hal. 70) , (Jawabmu Sunyi, hal. 68) dan (Pangiilan Moksa, hal. 67)
8. Joezefhine Maria – Joezefhine Zejoe, cinta adalah nafas terkuat yang hadir dalam sajak-sajaknya. Menegaskan cinta meski terabaikan, bagi kekasih, bagi sesama dan bagi orang orang yang kehilangan (Berkata Waktu Yang Akan Datang, hal.76), (Aksara Tuk Sahabat, hal.78) dan (Bocah Bocah Kolong, hal. 79).
9. Lina Kelana, dalam beberapa puisinya ia berani menggunakan diksi yang cukup tabu, hingga kita merasakan amarah mengalir dari beberapa puisinya (Arumi, hal.85), (Di Kesempuranaan Ini Tuhan Tak Lagi Bermaterai, hal. 90) . Namun juga Lina mampu mencipta imaji yang indah lewat diksi diksi santun dan lembut menyentuh (Dawai Getar Hati, hal. 88) dan (Engkau dan Selembar Kisah, hal. 91).
10. Eka Yuli Windya Astuti- Windy Aurora,
Windy mengolah tema maut dengan pilihan metafora unik, yaitu perjalanan kereta api (Pulang Naik Kereta, hal. 104). Maut merupakan tema yang menghantui puisi-puisi Windy, sebagai ujung dari perjalanan waktu yang tidak tercegah, sebagaimana yang tersirat dalam puisi Kertas (hal. 97) dan Lapuk (hal. 105).
Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa semua penyair di atas mengangkat tema tema yang sama tentang cinta, sepi, kehilangan juga harapan tetapi hasilnya akan tetap berbeda sebab masing masing memiliki personalitas yang ditentukan dari daya kreatifitas mereka dimana puisi merupakan manifestasi langsung dari metabolisme mental.*
(Susy Ayu)
di PDS HB Jassin, Jakarta, Sabtu, 15 Mei 2010)
Tarian Ilalang, sebuah judul buku yang menarik. Kemudian terbayang di benak tentang sekumpulan ilalang , tampak rapuh namun tegak dan oleh angin mereka bergerak sangat dinamis, teratur dan mampu bertahan dalam kekeringan. Ilalang serupa kecemasan sekaligus harapan abadi manusia.
Tarian Ilalang, adalah sebuah buku antologi puisi. Antologi secara harfiah diturunkan dari kata bahasa Yunani yang berarti “karangan bunga” atau “kumpulan bunga”, adalah sebuah kumpulan dari karya-karya sastra. Sementara kata puisi, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani poites, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat.
Kita bisa menyebut beberapa nama: Samuel Taylor Coleridge, Wordsworth, atau Dunton yang memiliki pendapatnya masing masing tentang puisi. Demikian juga kita, setelah menciptakan puisi dengan menjalani proses prosesnya, maka menurut saya puisi adalah merupakan sublimasi gerak perasaan dan pikiran yang terekam dalam kata kata. Sublimasi yang saya maksud tentu saja semacam perenungan/pengendapan yang melahirkan bentuk baru setelah penghayatan.
Dengan kata lain puisi bisa berupa “potret kata kata” atas diri kita atau di luar itu yang berhasil ditangkap dengan mata dan rasa kemudian terolah di dalam bathin, hingga melahirkan pikiran atau gagasan gagasan tentang hal itu di dalam sebuah frame.
Tarian Ilalang, antoloi puisi oleh Adrian Kelana, Arther Panther Olii, Atan Wira Bangsa, Bagus Prana, Faris Al Farisi, Geg Neka, Ira Ginda, Joezefhine Zejoe, Lina Kelana, dan Windy Aurora.
1. Adrian Kelana, dalam pengelanaannya ia menguatkan jejaknya atas asa ( Secawan Anggur Rajahan, hal. 4) dan cinta kepada sesama ( Kemana Asap Tungku Itu, hal. 8 ) juga harapannya (Musafir Kelana, hal 10).
2. Arther Panther Olii, berhasil menggali kepedihannya hingga terasa begitu kental namun mengiris dengan sangat halus pada liris penutupnya : O, tidakkah kalian lihat telah lahir sajak paling pedih dari bening mataku? ( Dan Lahirlah Sajak Paling Pedih Dari Bening Mataku, hal. 18).
3. Safwan Nizar – Athan Wira Bangsa, menghidupkan sajak sajaknya dari perenungan yang digali antara dunia dalam bawah sadar dan dunia dalam kesadaran serta mengantar kita untuk merunduk lebih dalam atas keagungan Illahi ( Aku Mencari-Mu, hal. 26) dan (Tuhan dan Rabi, hal. 27).
4. Bagus Prana, menulis rasa kehilangan dan pencarian akan cinta kasih yang lengkap tak terbelah, menyentuh rasa kemanusiaan kita (Syair Sebuah Balada, Hal. 37) , (Terlepas Sebuah Tanya, hal. 38) dan (Janji Dermaga Biru, hal. 40).
5. Faris Al Farisi, dialog ringan kerap kita temukan pada sajak sajaknya, dan itu membentuk keunikan dalam imaji yang kental (Kremasi, hal. 45) dan (Tentang Batu 4, hal. 50).
6. Geg Neka, sajak sajaknya kerap irit diksi namun lincah dan memiliki makna pada keseluruhan bangunan puisinya. Sajaknya sangat dinamis, enerjik ( Pikiran, hal. 57), (Gelembung, hal. 58) dan tegas dalam lembutnya ( Lembayung, hal. 61).
7. Ira Ginda, nuansa gothic begitu kental membungkus pada kebanyakan puisinya, namun ia mampu membuat imaji imaji dalam gelap itu menjadi nyata di benak kita. Nuansa Romantika Gothic; yang mengungkapkan dunia cinta secara sensual dimana bisa menghasilkan jalinan yang kuat atau kadang tragis menyembul dari imaji imajinya (Kisah Rembulan Buta, hal. 65) dan (Pelacur Di Antara Kedua Kakimu, hal. 71). Dalam nuansa kelam itu Ira juga mampu memberi imaji yang lembut di dalam kehangatan yang miris (Secawan Teh Hangat, hal. 70) , (Jawabmu Sunyi, hal. 68) dan (Pangiilan Moksa, hal. 67)
8. Joezefhine Maria – Joezefhine Zejoe, cinta adalah nafas terkuat yang hadir dalam sajak-sajaknya. Menegaskan cinta meski terabaikan, bagi kekasih, bagi sesama dan bagi orang orang yang kehilangan (Berkata Waktu Yang Akan Datang, hal.76), (Aksara Tuk Sahabat, hal.78) dan (Bocah Bocah Kolong, hal. 79).
9. Lina Kelana, dalam beberapa puisinya ia berani menggunakan diksi yang cukup tabu, hingga kita merasakan amarah mengalir dari beberapa puisinya (Arumi, hal.85), (Di Kesempuranaan Ini Tuhan Tak Lagi Bermaterai, hal. 90) . Namun juga Lina mampu mencipta imaji yang indah lewat diksi diksi santun dan lembut menyentuh (Dawai Getar Hati, hal. 88) dan (Engkau dan Selembar Kisah, hal. 91).
10. Eka Yuli Windya Astuti- Windy Aurora,
Windy mengolah tema maut dengan pilihan metafora unik, yaitu perjalanan kereta api (Pulang Naik Kereta, hal. 104). Maut merupakan tema yang menghantui puisi-puisi Windy, sebagai ujung dari perjalanan waktu yang tidak tercegah, sebagaimana yang tersirat dalam puisi Kertas (hal. 97) dan Lapuk (hal. 105).
Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa semua penyair di atas mengangkat tema tema yang sama tentang cinta, sepi, kehilangan juga harapan tetapi hasilnya akan tetap berbeda sebab masing masing memiliki personalitas yang ditentukan dari daya kreatifitas mereka dimana puisi merupakan manifestasi langsung dari metabolisme mental.*
(Susy Ayu)
Selasa, 08 Mei 2012
Peradaban Kecil di Sebuah Kelas
Di tengah ekspansi pasar global yang semakin mengemuka dalam dekade terakhir, tentu muncul persoalan yang urgen: bagaimanakah kita mendidik generasi muda bangsa ini di tengah pergaulan bangsa-bangsa yang dikomandoi oleh pasar ini?
Jawaban yang umum dimunculkan adalah bagaimana mengajarkan ketrampilan ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap digunakan oleh dunia kerja. Tapi yang jarang disinggung adalah bagaimana mendidik calon penerus bangsa yang tidak hanya pintar, tapi juga bijak.
Bijak mungkin kata yang terdengar berlebihan, tapi kalau kita mengingat bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan harkat manusia, maka wawasan kebijakan inilah yang sesungguhnya merupakan gambaran ideal dari kualitas kemanusiaan. Karenanya, seyogyanya, wawasan inilah yang menjadi tujuan akhir dari dunia pendidikan.
Wawasan kebijakan ini merupakan hal yang terlalu luas untuk dibahas dalam tulisan yang bersahaja ini. Akan tetapi, saya ingin berbagi sekelumit pengalaman yang saya tempuh, berkenaan dengan salah satu produk peradaban yang mengekspresikan secara langsung kebijakan-kebijakan manusiawi, yaitu puisi.
Tulisan ini berangkat dari pengalaman saya sebagai narasumber dalam Pelatihan dan Apresiasi Puisi untuk siswa dan guru Sekolah Dasar di kabupaten Banyuasin (6-7 Maret 2012) dan Ogan Ilir (8 – 9 Maret 2012) Sumatera Selatan yang diadakan oleh Badan Bahasa Jakarta.
Wajah wajah yang antusias dari peserta baik siswa maupun guru menyambut kehadiran saya dan Nia Samsihono beserta staff. Sungguh permulaan yang baik, mempelajari puisi dengan hati yang terbuka. Hari pertama, tentu saja saya menyajikan tips-tips dasar cara membuat sebuah puisi yang tentu tidak mereka temukan di dalam buku pelajaran di sekolahnya. Mulai dari pemilihan ide, pemilihan kata, membangun baris puitik dsb. Berikut latihan membuat puisi secara spontan dan membuka forum tanya jawab sebanyak-banyaknya. Hasilnya cukup mengejutkan saya, rata-rata peserta mampu menangkap materi, menciptakan puisi dan saya diserbu dengan beragam pertanyaan yang cukup kritis dan detil. Apa yang kemudian bisa kita baca dari sana? Ini menunjukkan bahwa ada kerinduan untuk disapa sebagai sebuah pribadi. Bahwa khususnya anak didik ini adalah juga manusia, bukan sekedar angka statistik dalam administrasi pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan nasional seyogyanya menggarisbawahi tujuan kemanusiaan semacam ini.
Menurut pengakuan beberapa guru; mereka kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar terutama saat harus berbicara di sebuah forum yang resmi tanpa menggunakan teks. Tentu hal ini salah satunya adalah karena mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari sehingga perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia tidak begitu banyak dimiliki. Maka melalui pelatihan dan apresiasi puisi kali ini, di mana saya menggunakan puisi-puisi dalam bahasa Indonesia setidaknya kita bisa menghargai betapa pentingnya bahasa nasional. Bahasa nasional adalah ikatan terkuat yang merangkum identitas kebangsaan.
Dalam kaitan dengan keberagaman, maka bahasa nasional menjadi sebuah jembatan yang mengatasi ragam yang pada akhirnya mampu mempertautkan ragam-ragam. Mungkin tidak ada bangsa lain di dunia ini yang terdiri dari sukubangsa-sukubangsa yang demikian beragam seperti Indonesia. Keragaman ini bisa kita lihat sebagai sebuah hambatan, atau sebaliknya, sebagai sumber kekayaan budaya yang luar biasa. Dari ranah asal identitas kebangsaan yang semacam ini, bahasa pemersatu merupakan satu pilar kebudayaan yang harus dibangun sebaik-baiknya. Kata ‘dibangun’ mungkin sangat bias-pemerintah, akan tetapi maksud saya di sini adalah bahwa bahasa merupakan ranah penting yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan ini bukan hanya tanggung jawab negara semata-mata. Meskipun demikian, dari sudut pandang tata kelola negara, dunia pendidikan yang mengedepankan pengembangan kebahasaan tidak bisa dikesampingkan lebih jauh lagi.
Bahasa pemersatu memang sering terdengar klise dalam ekspansi bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang gila-gilaan belakangan ini, juga dalam gembar-gembor going global. Itulah mengapa bahasa pemersatu yang menegaskan identitas nasional justru menjadi semakin penting dan mendesak, agar manusia Indonesia tidak lenyap sepenuhnya dalam pasar global dan globalitas.
Dalam kerangka kepedulian semacam ini, maka Pelatihan dan Apresiasi Puisi untuk siswa dan guru Sekolah Dasar ini menemukan konteksualisasinya. Kegiatan ini membuat para guru merasa lega karena cukup menjawab kecemasan mereka selama ini; “Bagaimana kami bisa mengajarkan apresiasi puisi jika kami sendiri tidak tahu cara membuat puisi?”. Dua hari masa pelatihan untuk tiap kabupaten memang rasanya sangat cepat, namun dari hasil evaluasi dan dari pertanyaan juga pernyataan mereka telah menunjukkan dari tidak tahu menjadi tahu. Sebuah bekal dasar bagi para guru untuk menurunkan kepada anak didik yang lain. Tentu kreatifitas seorang guru sangat dibutuhkan agar semua mampu mengapresiasikan puisi, tidak memperlakukannya sebagai sebuah hapalan namun pemahaman.
Guru dan murid adalah sesama kolega pembaca yang berbagi pengalaman mental/batin dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Karya sastra tidak bisa diajarkan dalam pengertian seperti mengajarkan petunjuk teknis. Setiap apresiasi sah adanya apapun bentuknya dan tidak ada salah benar atas hal itu. Oleh karenanya apresiasi sastra selalu merupakan individual dan tidak bisa digeneralisasikan. Hanya dengan demikian sastra bisa mencapai kedalaman manusiawi yang menjadi dasar penciptaannya.
Mengapresiasi puisi, mampu mengolah rasa juga pikir. Puisi adalah olah raga mental yang tidak tergantikan dengan sains. Puisi mengemukakan satu wilayah yang ditinggalkan oleh ekspansi sains dan teknologi, bahwa dimensi kemanusiaan juga terdiri dari kepekaan tanggap individu terhadap lingkungannya. Bentuk-bentuk tanggap antar individu, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya inilah yang membangun karakter sebuah peradaban. Demikianlah kita mengenali puncak-puncak capaian peradaban manusia dari sastra yang diciptakannya.
Pada hari terakhir pelatihan puisi di kab Ogan Ilir dan Banyuasin Sumsel, saya meminta peserta membuat puisi dan membacakannya di depan kelas. Untuk kemudian membahasnya, menuntun mereka mengapresiasikan tiap puisi. Terlihat beberapa siswa tidak mampu menghadang linangan air mata membacakan puisi di depan kelas, puisi tentang ibunya belum lama meninggal dan tentang cinta kepada kedua orang tua. Membuat kami ikut terhanyut ke dalam puisi-puisi mereka.
Pertanyaan terakhir menutup pelatihan, saya mengajukan pertanyaan; "Apa yang adik-adik dan bapak ibu guru rasakan ketika selesai membuat puisi?" Mereka menjawab merasa lega dan bahagia. Sebagian tersenyum, sebagian terharu. Beberapa pasang mata menyimpan air mata, juga saya.
Itu pencapaian yang tampaknya kecil, tapi demikianlah sastra bekerja untuk sebuah senyuman atau setitik air mata. Hal-hal yang menjadikan seorang manusia tetap manusia. Hingga perlahan kecerdasan emosional mereka akan berkembang, kecerdasan intelektual dan kecerdasan mental menjadi seimbang.
*Susy Ayu, penyair dan cerpenis.
(Dimuat di Minggu Pagi Yogya No. 01 Th. 65, Minggu I April 2012)
Jawaban yang umum dimunculkan adalah bagaimana mengajarkan ketrampilan ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap digunakan oleh dunia kerja. Tapi yang jarang disinggung adalah bagaimana mendidik calon penerus bangsa yang tidak hanya pintar, tapi juga bijak.
Bijak mungkin kata yang terdengar berlebihan, tapi kalau kita mengingat bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan harkat manusia, maka wawasan kebijakan inilah yang sesungguhnya merupakan gambaran ideal dari kualitas kemanusiaan. Karenanya, seyogyanya, wawasan inilah yang menjadi tujuan akhir dari dunia pendidikan.
Wawasan kebijakan ini merupakan hal yang terlalu luas untuk dibahas dalam tulisan yang bersahaja ini. Akan tetapi, saya ingin berbagi sekelumit pengalaman yang saya tempuh, berkenaan dengan salah satu produk peradaban yang mengekspresikan secara langsung kebijakan-kebijakan manusiawi, yaitu puisi.
Tulisan ini berangkat dari pengalaman saya sebagai narasumber dalam Pelatihan dan Apresiasi Puisi untuk siswa dan guru Sekolah Dasar di kabupaten Banyuasin (6-7 Maret 2012) dan Ogan Ilir (8 – 9 Maret 2012) Sumatera Selatan yang diadakan oleh Badan Bahasa Jakarta.
Wajah wajah yang antusias dari peserta baik siswa maupun guru menyambut kehadiran saya dan Nia Samsihono beserta staff. Sungguh permulaan yang baik, mempelajari puisi dengan hati yang terbuka. Hari pertama, tentu saja saya menyajikan tips-tips dasar cara membuat sebuah puisi yang tentu tidak mereka temukan di dalam buku pelajaran di sekolahnya. Mulai dari pemilihan ide, pemilihan kata, membangun baris puitik dsb. Berikut latihan membuat puisi secara spontan dan membuka forum tanya jawab sebanyak-banyaknya. Hasilnya cukup mengejutkan saya, rata-rata peserta mampu menangkap materi, menciptakan puisi dan saya diserbu dengan beragam pertanyaan yang cukup kritis dan detil. Apa yang kemudian bisa kita baca dari sana? Ini menunjukkan bahwa ada kerinduan untuk disapa sebagai sebuah pribadi. Bahwa khususnya anak didik ini adalah juga manusia, bukan sekedar angka statistik dalam administrasi pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan nasional seyogyanya menggarisbawahi tujuan kemanusiaan semacam ini.
Menurut pengakuan beberapa guru; mereka kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar terutama saat harus berbicara di sebuah forum yang resmi tanpa menggunakan teks. Tentu hal ini salah satunya adalah karena mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari sehingga perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia tidak begitu banyak dimiliki. Maka melalui pelatihan dan apresiasi puisi kali ini, di mana saya menggunakan puisi-puisi dalam bahasa Indonesia setidaknya kita bisa menghargai betapa pentingnya bahasa nasional. Bahasa nasional adalah ikatan terkuat yang merangkum identitas kebangsaan.
Dalam kaitan dengan keberagaman, maka bahasa nasional menjadi sebuah jembatan yang mengatasi ragam yang pada akhirnya mampu mempertautkan ragam-ragam. Mungkin tidak ada bangsa lain di dunia ini yang terdiri dari sukubangsa-sukubangsa yang demikian beragam seperti Indonesia. Keragaman ini bisa kita lihat sebagai sebuah hambatan, atau sebaliknya, sebagai sumber kekayaan budaya yang luar biasa. Dari ranah asal identitas kebangsaan yang semacam ini, bahasa pemersatu merupakan satu pilar kebudayaan yang harus dibangun sebaik-baiknya. Kata ‘dibangun’ mungkin sangat bias-pemerintah, akan tetapi maksud saya di sini adalah bahwa bahasa merupakan ranah penting yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan ini bukan hanya tanggung jawab negara semata-mata. Meskipun demikian, dari sudut pandang tata kelola negara, dunia pendidikan yang mengedepankan pengembangan kebahasaan tidak bisa dikesampingkan lebih jauh lagi.
Bahasa pemersatu memang sering terdengar klise dalam ekspansi bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang gila-gilaan belakangan ini, juga dalam gembar-gembor going global. Itulah mengapa bahasa pemersatu yang menegaskan identitas nasional justru menjadi semakin penting dan mendesak, agar manusia Indonesia tidak lenyap sepenuhnya dalam pasar global dan globalitas.
Dalam kerangka kepedulian semacam ini, maka Pelatihan dan Apresiasi Puisi untuk siswa dan guru Sekolah Dasar ini menemukan konteksualisasinya. Kegiatan ini membuat para guru merasa lega karena cukup menjawab kecemasan mereka selama ini; “Bagaimana kami bisa mengajarkan apresiasi puisi jika kami sendiri tidak tahu cara membuat puisi?”. Dua hari masa pelatihan untuk tiap kabupaten memang rasanya sangat cepat, namun dari hasil evaluasi dan dari pertanyaan juga pernyataan mereka telah menunjukkan dari tidak tahu menjadi tahu. Sebuah bekal dasar bagi para guru untuk menurunkan kepada anak didik yang lain. Tentu kreatifitas seorang guru sangat dibutuhkan agar semua mampu mengapresiasikan puisi, tidak memperlakukannya sebagai sebuah hapalan namun pemahaman.
Guru dan murid adalah sesama kolega pembaca yang berbagi pengalaman mental/batin dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Karya sastra tidak bisa diajarkan dalam pengertian seperti mengajarkan petunjuk teknis. Setiap apresiasi sah adanya apapun bentuknya dan tidak ada salah benar atas hal itu. Oleh karenanya apresiasi sastra selalu merupakan individual dan tidak bisa digeneralisasikan. Hanya dengan demikian sastra bisa mencapai kedalaman manusiawi yang menjadi dasar penciptaannya.
Mengapresiasi puisi, mampu mengolah rasa juga pikir. Puisi adalah olah raga mental yang tidak tergantikan dengan sains. Puisi mengemukakan satu wilayah yang ditinggalkan oleh ekspansi sains dan teknologi, bahwa dimensi kemanusiaan juga terdiri dari kepekaan tanggap individu terhadap lingkungannya. Bentuk-bentuk tanggap antar individu, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya inilah yang membangun karakter sebuah peradaban. Demikianlah kita mengenali puncak-puncak capaian peradaban manusia dari sastra yang diciptakannya.
Pada hari terakhir pelatihan puisi di kab Ogan Ilir dan Banyuasin Sumsel, saya meminta peserta membuat puisi dan membacakannya di depan kelas. Untuk kemudian membahasnya, menuntun mereka mengapresiasikan tiap puisi. Terlihat beberapa siswa tidak mampu menghadang linangan air mata membacakan puisi di depan kelas, puisi tentang ibunya belum lama meninggal dan tentang cinta kepada kedua orang tua. Membuat kami ikut terhanyut ke dalam puisi-puisi mereka.
Pertanyaan terakhir menutup pelatihan, saya mengajukan pertanyaan; "Apa yang adik-adik dan bapak ibu guru rasakan ketika selesai membuat puisi?" Mereka menjawab merasa lega dan bahagia. Sebagian tersenyum, sebagian terharu. Beberapa pasang mata menyimpan air mata, juga saya.
Itu pencapaian yang tampaknya kecil, tapi demikianlah sastra bekerja untuk sebuah senyuman atau setitik air mata. Hal-hal yang menjadikan seorang manusia tetap manusia. Hingga perlahan kecerdasan emosional mereka akan berkembang, kecerdasan intelektual dan kecerdasan mental menjadi seimbang.
*Susy Ayu, penyair dan cerpenis.
(Dimuat di Minggu Pagi Yogya No. 01 Th. 65, Minggu I April 2012)
NOTA PERKAWINAN
I. PA
AKU bisa merasakannya. Ia mengelus sepanjang sumsum tulang belakangku dan tiap kali ia bergerak sebentuk rasa lelah merayapiku. Aku membayangkan ribuan sel yang bertarung satu sama lain. Sementara pertempuran itu sendiri sesungguhnya tidak memenangkan apapun. Sayangnya, aku hanya bisa sekarat dengan seorang istri yang khianat.
“Pa, dengarkan, kau akan segera mati, tapi jangan takut!” katanya sambil menggenggam tanganku. Matanya pasti.
Aku menoleh padanya. Tersenyum mungkin, aku tak tahu benar. Tapi dengan tatapan mataku, aku mencoba mengiyakan kata-katanya. Aneh, menjelang mati, orang menjadi sangat sabar. Sebagian kedirianku sudah berpindah ke matra lain, dan ia belum pernah sekarat sekalipun. Ia cuma istriku, yang bertambah demikian ranum pada usia tiga puluh enamnnya dengan mulut yang kebetulan manis. Juga pintar dengan banyak cara bersenang-senang. Bagaimana mungkin ia bicara tentang keberanian dan ketakutan yang bisa hadir sesudah kematian? Tapi menjelang maut, orang sudah terlalu lelah untuk berbantahan. Demikian juga aku.
“Aku baik-baik saja. Percayalah”, lalu, agar dramatis, kukutip sebuah sajak, “Kematian cuma selaput gagasan yang gampang diseberangi.1” Mungkin aku cuma berpikir aku mengatakan itu. Mungkin suaraku tidak lagi terdengar. Satu hentakan napas lagi, aku akan menjadi batu meteor yang menghempas ke pusat daya tarik dan menyediakan diri untuk terbakar punah. Tanpa aduh dengan sejumlah alat pemantau organ dijejalkan ke tubuhku.
Di sisi ranjangku, istriku terhenyak mundur dalam kengerian. Mereka yang pernah sekarat akan tahu, melihat seseorang yang begitu menderita menyaksikan proses itu jauh lebih menyakitkan daripada menempuh sekarat itu sendiri.
Memikirkan istriku membuatku diserang perasaan malu, sebab sesungguhnya, ia adalah orang yang paling kubenci sepanjang hidupku. Satu-satunya orang yang lebih buruk dari sekawanan serigala untuk berjaga di sisi ranjang kematianku. Tapi sakit yang mengalihkan penderitaanku itu cuma membuktikan bahwa aku peduli pada derita dan bahagianya. Aku merasa amat hina untuk mempunyai perasaan itu, dalam pergulatan dengan maut yang akan membebaskanku dari cinta dan benci, aku mencoba melawan perasaan peduliku padanya.
Kurasakan istriku tersentak dan melepaskan genggamannya. Di sisi ranjang, kulihat ia membekap mulutnya dan dengan mata penuh belas kasih yang terhunjam-hunjam kengerian, kulihat ia merapalkan doa. Dan doa, terutama bila itu doa yang keluar dari mulutnya, bagiku adalah doa paling terkutuk yang pernah terjadi di kolong langit. Aku menjerit sejadinya untuk menolakkan itu. ***
II. MA
Cuma senggama yang bisa menghasilkan gerakan lebih baik dari ini. Beberapa di antaranya mengingatkanku pada itu. Punggungnya melengkung ke atas ranjang, matanya membeliak dan setetes air mengambang di sudut matanya. Dan cengkeraman jari-jarinya, ah! Aku merapatkan kedua kakiku. Mencari sesuatu. Sungguh tidak sopan, kataku sendiri dalam hati. Tapi aku tidak sanggup menahankan perasaan ini, meskipun aku seorang istri baik-baik. Dan di usiaku yang ketiga puluh enam, susuku masih sekencang delima, hanya saja dengan suami megap-megap macam ini aku merasa agak tersinggung. Tapi ia sekarat, aku bisa melihatnya.
Perasaanku berdebar. Di balik pintu, kekasihku menunggu dengan simpati yang sempurna. Selama suamiku menarik napasnya satu-satu dalam delapan belas jam ini, ia telah menyentuhkan telapak tangannya yang terasa hangat empat kali ke pinggulku, meremasnya, tiap kali aku beranjak untuk mengistirahatkan diriku sendiri ke luar ruangan. Ia tahu itu menciptakan perasaan riang yang bergelora dalam diriku.Usianya dua puluh tujuh tahun. Mengingat staminanya yang kuukur secara rahasia dalam penyelinapan-penyelinapan kami, aku bisa merasakan, waktu sekaratnya masih akan lama lagi.
Tapi pikiran itu membuatku mendengus. Dua belas tahun lalu yang lalu, aku berpikir begitu juga atas laki-laki dalam ruangan ini. Tapi lihatlah, sekali kau melihat rambutnya yang rontok dan menampakkan kulit kepalanya yang lunak kemerahan, praduga-pradugamu bisa saja salah, dan itu menjengkelkan. Aku begitu jengkel hingga aku harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Bila ia bertumpuk, maka keraknya akan menjadi dendam. Seperti juga hujan dan pengetahuan, dendam mengharuskanmu berbuat sesuatu. Tapi aku menjalankan tugasku dengan baik. Tatapanku selembut Cinderella, dan dengan itu aku mengusap keningnya, memandangnya penuh kasih, tak ada yang meragukannya, seorang pendeta sekalipun.
O ya, pendeta. Telah kusiapkan satu di sudut ruang. Ia membacakan doa-doa, untuk kematian yang pasti akan datang, untuk membebaskannya dan lebih-lebih, membebaskanku. Tak lupa, sambil kuseka keningnya, kubisikkan kata-kata lembut yang tak terdengar siapapun kecuali dia, bahwa kematian tidaklah semenakutkan itu. Akan hal kebenarannya, aku tidak peduli. Sungguh tidak sopan mempertanyakan kebenaran dalam saat semacam ini. Semua orang menjalankan perannya dengan baik. Juga dia, lihatlah! Sekaratnya meyakinkan. Kepura-puraan selalu membuatku bergairah. Arus kebencian itu menenangkanku. Ia laki-laki yang baik, tentu saja. Tapi cinta yang gagal selalu membuat semuanya pahit. Ingatan akan ranjang yang patah serta ciuman-ciuman yang panas di saat-saat awal pernikahan kami, gampang sekali pupus oleh sakit hati.
Aku menoleh sekeliling. Foto pernikahan kami di atas ranjang. Sejumlah peralatan yang menyumpal kepala dan urat nadinya, lalu juga sejumlah kartu ucapan di keranjang-keranjang yang berharap kematiannya tak sepasti ini. Ia orang penting. Tapi tak sepenting itu bila ia sudah menjadi mayat. Usai pemakaman dan tanda duka di ujung jalan, segalanya akan kembali seperti biasa. Pun cuaca tidak akan menunggu. Hidup terus berlangsung, dengan laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun di balik pintu yang bengalnya membangkitkanku.
Menikah, terlebih-lebih menikah dengan suamiku, adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Laki-laki gampang didapatkan, dan sering-sering berhadiah payung pula. Akan halnya sebab musabab kebencianku padanya, dan ketidaksopananku menceritakan ini semua, sungguh tidak tepat menceritakannya sekarang. Maafkan aku untuk melewatkan cerita semanis itu. Sebuah sentakan kuat menarik tanganku, kulihat ia menoleh dan membeliakkan matanya ke arahku lebar-lebar. Sedetik, aku bisa merasakan hawa kebencian yang telah kami pupuk bersama berseliweran di antara kami. Ah, terkesiap aku merasakan cerlangnya.
“Pa, tenanglah. Kuatlah. Kau begitu dikasihi oleh-Nya,” kataku lembut-lembut. Kupikir aku agak payah kali ini. Ia masih menatapku. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Pendeta mendongakkan kepalanya sejenak. Beberapa paramedik yang mendekat dengan agak panik kutahan dengan isyarat. “Sudah sampaikah?” tanyaku di telinganya. Tak seorangpun bisa mendengarnya. Pun aku tak yakin ia bisa mendengarku. Tapi kami disatukan kebencian. Dengan itu kami bertukar pesan dengan baik selama ini. Lalu sebuah guncangan kecil yang membuatku berpikir bahwa seseorang tengah mencekiknya beruntun hinggap seperti sebuah irama. Harus kuakui, harap-harap cemasku memuncak pada saat itu.
Aku istri yang baik. Tapi aku tidak bisa hidup dengan suami yang sekarat selama lebih dari lima tahun. Aku berhak untuk harap-harap cemas sekarang ini. Ah, orang berhak berpikir untuk berbahagia dalam situasi ini. Apalagi setelah sebuah upacara pemakaman yang megah.
Aku menatap matanya. Oh mata kebencian itu, dalam tatapan semacam ini tepat sebelum maut, kami disatukan. Kukuatkan tatapanku, tepat ke pupil matanya. Beberapa detik sebelum cerlang sinar kebenciannya meredup dan padam sama sekali, aku amat yakin bahwa ia tahu, aku tidak memaafkannya.
III. PA
Dengan sedih aku melihatnya menatapku tepat ke pupil mataku, seperti ia menatapku dulu, dua belas tahun yang lalu, dan merampas cintaku. Kuperas tiap jengkal kebencian dari seluruh sel-selku yang masih terus berbunuhan dengan sengit, berharap itu terpancar dari mataku, melesat sebagai anak panah, dan menghabisi cintanya. Tapi dengan lembutnya, ia meletakkan telapak tangannya kembali ke keningku. Di usapnya keringatku. Di dekatkannya mulutnya ke telingaku. Dirapalkannya doa, lambat-lambat, dan dijadikannya aku seekor babi yang dipanggang di atas api hidup-hidup.
Aku membencimu, Ma, jangan doakan aku. Biarkan aku mati dalam kebencian, sebab kebencianku padamu adalah satu-satunya hal yang memberi makna pada hidupku. Jangan pupus ini dengan cintamu, jangan jadikan hidupku sia-sia. Kupikir ia bisa membaca pikiranku. Tapi ia terus menatapku, seakan aku adalah satu-satunya hal yang bisa terjadi di dunia ini dan seluruh kediriannya berkerumun dalam tatapan matanya. Sementara rasa dingin itu menjalar dan membuncah di ubun-ubunku, kesimpulan-kesimpulanku mengabur bergelombang bersama seluruh sedih dan bahagia yang pernah terjadi dalam hidupku. Tergulung di dalamnya adalah rasa putus asa yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang sekarat, menanti tanda terakhir kebencian dari perempuan yang kunikahi dua belas tahun lalu, yang akan melengkapkan dendamku. Aku menunggu seperti Musa di bukit Sinai.
Tidak, Ma, jangan maafkan aku, jangan sekali-kali kaumaafkan kita. Tidak atas nama masa lalu, tidak atas nama anak-anak kita, tidak atas nama cinta, tidak atas nama hidup yang hendak berakhir, tidak atas nama masa depan. Tidak, Ma, jangan…***
Tepat dalam satu kerdipan mata setelah detik kematian laki-laki itu, dengan satu desis tajam penghabisan, istri yang kelelahan dan diserang rasa bosan yang cuma bisa dipahami oleh orang-orang yang pernah berada dalam pernikahan itu membisikkan ini ke telinga suaminya: “Matilah kau, Pa, aku membencimu demikian hingga aku bersedia tulang sumsumku membusuk karenanya…”
Di balik pintu, laki-laki dua puluh tujuh tahun yang sanggup menerbitkan perasaan riang dalam diri Ma itu terpekur diam dengan ketakziman yang tak bisa kita pahami. ***
catatan kaki : [i] Daerah Perbatasan; Soebagyo Sastrowardoyo
Pernah dimuat di Suara Karya, 8 Oktober 2011
dan di dlm buku Kumpulan cerpenku "Perempuan Di Balik Kabut"
Langganan:
Postingan (Atom)